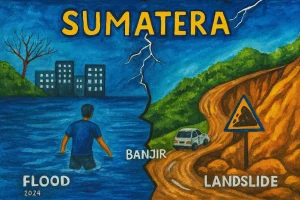MAKLUMAT — Masalah dalam judul di atas adalah keprihatinan atas sejumlah kejadian atau kasus sebagai fakta sosial yang menunjukkan adanya krisis atau peluruhan moral dan etika luhur bangsa akhir-akhir ini.
Kasus paling menonjol ialah diberhentikannya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mewakili erosi moral dan etika para pejabat negara atau pejabat publik.
Kasus paling baru mundurnya unsur pejabat pemerintahan sekaligus tokoh agama karena menyentuh persoalan kepatutan etika dalam berinteraksi sosial dengan sesama.
Kita masih dapat mendaftar persoalan bangsa yang bersifat struktural seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, politik transaksional, dan persoalan-persoalan politik yang juga menyentuh ranah moral dan etika.
Romo Magnis Suseno: “Saya merasa prihatin dengan situasi di negara kita ini. Kiranya perlu kita serukan kembali agar etika mendapat tempatnya, kita ingin bahwa bukan hanya kepentingan kekuasaan mereka yang berkuasa.”. Rohaniawan ternama itu menganjurkan agar “Etika Bernegara Mesti Diperbaiki” (https://epaper.mediaindonesia.com/detail/etika-bernegara-mesti-diperbaiki, diunduh 11/12/2024).
Dimensi moral dan etika dalam kehidupan suatu masyarakat atau bangsa tidak dapat dipandang enteng karena representasi dari martabat ruhani dan akal-budi manusia. Persoalan moral dan etika tersebut tidak dapat dimarjinalisasikan sebagai urusan domestik dan privat, sebab dalam kehidupan bangsa yang dikenal maju dan sekuler-modern pun keduanya masih dijunjung tinggi.
Betapa sejumlah kasus menunjukkan, seorang pejabat tinggi hingga Perdana Menteri mundur karena tersangkut persoalan etika jabatan dan etika publik. Apalagi dalam kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki pijakan utama nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa.
Menurut Syeikh Ahmad Syauqi dalam salah satu syairnya: “Bahwasanya kejayaan bangsa itu tergantung akhlaknya, bila akhlaknya rusak maka jatuhlah bangsa itu”. Sejalan prinsip etika deontologis dari Emanuel Kant, bahwa etika mengutamakan kewajiban moral sebagai dasar untuk menilai kebaikan atau keburukan suatu tindakan.
Ketika standar nilai baik dan buruk semakin longgar, maka terjadi sikap permissive yakni serba membolehkan apa saja (anything goes), seperti pelanggaran hukum dengan mudah dibenarkan dengan membawa ke area abu-abu atau “grey area”.
Legitimasi atas berbagai pelanggaran tersebut dapat berkembang menjadi permisivisme, yakni suatu pandangan 4 yang membolehkan dan mengizinkan segala hal tanpa pondasi nilai yang kokoh.
Masalah Mentalitas
Problem etika dan moral terkait dengan kondisi mentalitas yang masih melekat dengan kelemahan karakter masyarakat Indonesia. Koentjaraningrat (1987) telah lama mengingatkan kelemahan mentalitas manusia Indonesia, di antaranya suka meremehkan mutu, menerabas, tidak percaya kepada diri sendiri, tidak berdisiplin murni, dan suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh.
Kelemahan mentalitas serupa dikemukakan oleh budayawan Mochtar Lubis (2016) yang menunjuk ciri manusia Indonesia yaitu hipokrit alias munafik, enggan bertanggung jawab atas perbuatan dan keputusannya, berjiwa feodal, percaya takhayul, dan artistik yang cenderung erotik.
Tanpa bermaksud menggeneralisasi dan peluang perubahan dalam mentalitas orang Indonesia ke arah yang positif, peringatan dua tokoh tersebut penting menjadi bahan introspeksi bagi seluruh elite dan warga bangsa.
Masalah Kebudayaan
Masalah moral dan etika dalam mentalitas bangsa sebenarnya masalah kebudayaan, yakni menyangkut sistem pengetahuan kolektif manusia dalam kehidupan bersama.
Masyarakat Indonesia menampilkan gaya hidup baru yang menunjukkan anomie atau anomali, yakni penyimpangan perilaku dalam masyarakat. Ketika korupsi, orientasi materi (materialisme), transaksi politik uang, memuja kesenangan duniawi (hedonisme), dan cara hidup menghalalkan apa saja (oportunisme) mulai meluas dalam 5 kehidupan masyarakat maka yang terjadi ialah ketercerabutan.
Menurut William Ogburn terjadi “cultural lag”, yakni ketika budaya fisik-materi makin domin mengalahkan segala hal yang bersifat ruhani, sehingga mereka mengalami kerapuhan mentalitas. Kenapa terjadi? Dalam konteks perubahan perilaku masyarakat yang menurut Alvin Toffler mengalami lompa budaya (future shock) akan terjadi fenomena kehilangan arah (disorientation), sehingga mereka tidak tahu mana yang benar dan salah, baik dan buruk, pantas dan tidak pantas.
Francis Fukuyama menyebutnya sebagai “great disruption” atau prahara sosial-budaya yang meluas, sedangkan Peter L Berger melabeli sebagai fenomena “chaos” yakni situasi kehidupan yang kacau-balau dalam sistem nilai masyarakat.
Dalam analisis Berger (1983), manusia modern mengalami “anomie” yakni “suatu keadaan di mana setiap individu manusia kehilangan ikatan yang memberikan perasaan aman dan kemantapan hidup dengan sesamanya, sehingga kehilangan petunjuk dan makna hidup yang berarti”.
Kondisi anarkistik tersebut dalam teori kebudayaan klasik Ranggawarsito disebut “zaman edan” (zaman kegilaan): “Sekarang zamannya zaman gila. Kalau tidak gila tidak dapat bagian. Seberuntung-beruntungnya orang yang gila itu, masih lebih beruntung orang yang ingat dan waspada”.
Dalam kehidupan bernegara, Pujangga ternama tersebut menulis: “Sekarang martabat negara, tampak telah sunyi sepi, sebab rusak 6 pelaksanaan peraturannya, karena tanpa teladan, orang meninggalkan kesopanan, para cendekiawan dan para ahli terbawa hanyut dalam zaman bimbang, bagaikan kehilangan tanda-tanda kehidupannya, kesengsaraan dunia karena tergenang halangan.” (Kuntowijoyo, 1999).
Jika ingin memperbaiki dan menata kembali kehidupan kebangsaan yang bermakna, maka diperlukan langkah transformasi dalam dimensi mentalitas dan kebudayaan bangsa Indonesia di dua level: Individual dan kolektif atau melalui sistem nilai budaya.
Transformasi mentalitas menuju manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila, beragama, dan berkebudayaan luhur bangsa dalam bentuk keteladanan dari para tokoh wibawa. Tokoh agama, tokoh adat, para begawan ilmu di kampus, hingga para tokoh bangsa penting menjadi sosok-sosok teladan yang dapat diikuti praktik hidupnya, lebih dari sekadar berkata-kata, yang menurut Buya Syafii Maarif penting menunjukkan konsistensi “kata sejalan tindakan”.
Para elite itu memiliki kekuatan sosial dan “kharisma” sebagai rujukan berperilaku warga. Kehadirannya mesti apa adanya (genuine, autentik), tidak entertainment di atas panggung populisme.
Role Model Keteladanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Banyak kesaksian para tokoh nasional dari berbagai golongan yang mengakui keteladanan Sultan IX, sebagaimana terekam dalam buku “Tahta Untuk Rakyat”. Betapa luhur HB IX menghadirkan contoh baik tentang sikap kenegarawanan dan keluhuran budi yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan dinasti. Sikap hidupnya autentik, menjadi mutiara berharga bagi seluruh bangsa Indonesia.
Kesaksian Mochtar Lubis dalam Pengantar Buku “Takhta Untuk Rakyat” memberikan catatan penting. Ketika Sri Sultan HB IX menjatuhkan pilihan politik memilih Negara Republik Indonesia ketimbang bujuk rayu Belanda, sungguh merupakan langkah yang sangat besar sekaligus menunjukkan konsistensi sikap kenegarawanannya.
Mochtar Lubis memberikan kesaksian berikut: “Belanda tidak berhasil sama sekali membujuknya dengan berbagai tawaran yang muluk-muluk. Dan Sultan Hamengku Buwono IX, pada setiap saat kritis dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia melawan kembalinya kekuasaan penjajah Belanda dan kemudian setelah kemerdekaan dapat direbut kembali, senantiasa hadir dan melakukan kewajibannya dengan tenang, penuh keyakinan, dan keberanian. Ia bukan tokoh pemimpin yang gembar-gembor, tetapi kehadirannya membawa keyakinan perjuangan yang mantap.”
Menurut Mochtar Lubis: “kesederhanaan sikapnya, tingkah lakunya yang amat demokratis, dan terasa amat wajar.” Pemikiran dan pengetahuan Sri Sultan IX sangatlah luas. Di balik kesederhanaannya, tulis Lubis “Ia menyembunyikan pikiran yang amat terbuka pada dunia sekelilingnya … Ia banyak tahu tentang apa yang terjadi di negeri ini”.
Lebih khusus Mochtar Lubis bersaksi, “Satu lagi yang berkesan pada saya ialah betapapun ia tidak menyetujui sesuatu atau kelakuan seseorang, maka “Bung Sultan” tidak pernah saya dengar mempergunakan kata-kata yang keras dalam mengomentarinya. Paling banyak ia tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya.”
Potensi Kebaikan Manusia Indonesia
Manusia Indonesia yang berkarakter kuat dan memiliki sikap luhur sebenarnya masih banyak, yang diperlukan mobilisasi potensi kebaikan budi luhur. Bangsa Indonesia masih memiliki nilai-nilai keutamaan yang mengkristal menjadi modal sosial dan budaya penting. Di antara nilai-nilai itu adalah daya juang, tahan menderita, mengutamakan harmoni, dan gotong royong.
Nilai-nilai keutamaan tersebut masih relevan, namun memerlukan penyesuaian dan pengembangan sejalan dengan dinamika dan tantangan zaman serta meniscayakan proses transformasi mentalitas baru. Transformasi mentalitas melalui peran ketokohan dapat diperluas dengan memobilisasi potensi-potensi kebaikan yang hidup di lingkungan elite dan warga dari berbagai golongan, yang masih memiliki akar nilai yang baik.
Artinya, meski sebagian pesimistik karena memandang parahnya persoalan mentalitas yang saat ini diidap masyarakat di tingkat elite maupun warga, namun selalu terbuka pada perubahan atau transformasi mentalitas antara lain dengan menghadirkan figur-figur baik di berbagai komunitas lingkungan sosial yang dapat menjadi suri teladan di ruang publik.
Pandangan baru dalam perkembangan teori sosial dikemukakan oleh Rutger Bregman (2019) dalam karyanya “Human Kind”. Menurut Bregman manusia pada dasarnya baik. Teori tersebut merupakan antitesis terhadap pandangan manusia pada dasarnya buruk sebagaimana teori “veneer theory” (teori lapis luar) yang dikembangkan ahli biologi Frans de Waal yang menyatakan pada hakikatnya manusia itu egois, agresif, dan cepat panik.
Demikian halnya dengan teori di dunia ekonomi, yang menisbahkan manusia sebagai “homo economicus”, yakni makhluk yang pikiran, sikap, dan tindakannya hanya mengejar keuntungan sendiri bagaikan robot pemburu kerakusan laba dalam hidup tanpa menimbang dimensi lainnya.
Bregman mengajukan gagasan radikal yang disebutnya “new realism” (realisme baru) atas potensi baik manusia untuk dikembangkan sebagai antitesis dari kehidupan sarat tragedi dalam sejarah manusia modern. Dalam pandangan Bregman, kepercayaan terhadap kebaikan dan altruisme dapat mengubah cara manusia berpikir (human kind) yang memberi harapan bagi kehidupan manusia ke depan.
Meskipun, menurut catatan Bregman, banyak orang di Amerika Serikat dan Jerman misalnya, tidak mempercayainya. Kekejaman Hitler menjadi trauma sejarah yang kelam bagi dunia kemanusiaan, yang melahirkan tragedi “Auschwitz” di masa lalu atau genosida di 10 Gaza pada saat ini, yang keduanya lahir di era dunia modern yang berwawasan antroposens atau serba manusia.
Realisme Baru ala Bregman dengan Hadis Nabi dari Abu Hurairah, yang artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah” (Riwayat Muslim). Fitrah beragama yang suci d bersih (QS Al-A’raf: 172).
Strategi kedua: Transformasi Mentalitas Kolektif melalui pengembangan Sistem Sosial Budaya. Bangsa Indonesia mempunyai sejarah dan kebudayaan yang terbilang bertradisi-besar (great tradition), dengan kebudayaan yang luhur terutama dalam tata krama dan pergaulan antar sesama maupun warisan kebudayaan fisik yang cemerlang. Jejak sejarah kebudayaan fisik seperti masjid, candi, kraton, kain batik, keris, phinisi, dan peninggalan-peninggalan budaya lainnya (heritage) mendukung kebudayaan masa lampau bangsa ini.
Berbagai kerajaan yang pernah jaya di Nusantara seperti Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Kutai, Sriwijaya, Singosari, Demak, Pajang, Banten, Majapahit, Mataram, dan lain-lain menunjukkan jejak kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia yang gemilang.
Kendati diakui, bangsa ini juga mengalami masa penjajahan yang terbilang lama dan berat sejak Portugis datang tahun 1509 dan berhasil menjatuhkan Malaka tahun 1511, hingga penjajahan Belanda yang sangat panjang dari tahun 1800 sampai 1942, serta pendudukan singkat Jepang tahun 1942-1945 yang berujung pada kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
Tantangan Globalisasi dan Modernisasi Tahap Lanjut (Postmodern)
Tantangan ini meniscayakan orientasi kepada kualitas, persaingan dan daya saing sehingga menuntut bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersifat kompetitif, dinamis, berkemajuan, dan berkeunggulan dengan tetap berpijak pada nilai dan kepribadian sendiri.
Karena itu cukup mendesak untuk dilakukan transformasi karakter bangsa, yaitu dengan memelihara dan meningkatkan nilai-nilai keutamaan yang sudah terbangun sejak dahulu dan mengembangkan nilai-nilai keutamaan baru, termasuk membuka diri terhadap nilai-nilai keutamaan bangsa-bangsa lain yang lebih maju.
Kelemahan mentalitas manusia Indonesia antara lain karena faktor nilai budaya negatif dan inferior yang diwariskan penjajah kepada bangsa Indonesia. Masalah penyakit mentalitas tersebut sebenarnya dapat diperbaiki dengan menanamkan nilai-nilai dalam Sistem Nilai Budaya (Culture Value System) masyarakat Indonesia, yang terdiri dari konsepsi-konsepsi, yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup (Koentjaraningrat, 1987).
Dalam perubahan sistem kebudayaan Indonesia sangat dimungkinkan mengintegrasikan nilai-nilai keindonesiaan dengan nilai-nilai Barat modern yang konstruktif sebagaimana Pidato Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam penobatannya tanggal 18 Maret 1940 di Yogyakarta, seperti sebagian cuplikan berikut: “Sepenuhnya saya menyadari bahwa tugas yang ada di pundak saya adalah sulit dan berat, terlebih-lebih karena ini menyangkut mempertemukan jiwa Barat dan Timur agar bekerja sama dalam suasana harmonis, tanpa yang Timur harus kehilangan kepribadiannya…” (Atmakusumah, 2011).
Transformasi manusia Indonesia yang cerdas dan berkarakter kuat dalam konteks kekinian dicirikan oleh religiusitas yang kokoh, kapasitas intelektual dan penguasaan iptek yang lengkap disertai mentalitas unggul seperti keterpercayaan, ketulusan, kejujuran, keberanian, ketegasan, ketegaran, kemandirian, serta kuat dalam memegang prinsip dan sifat-sifat khusus lainnya.
Indonesia emas tahun 2045 akan terwujud jika generasi mudanya saat ini religius, cerdas, berkepribadian Indonesia yang unggul seperti itu. Bukan generasi lemah, pembebek, serba instan, menjadi benalu, penjual populisme murah, serta tidak memiliki khazanah keilmuan, kepribadian, dan perilaku serba utama.
Transformasi nilai dan mentalitas Pancasila
Transformasi mentalitas dan kebudayaan Indonesia dengan modal ruhaniah dan sosial yang dimiliki meniscayakan transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Buya Syafii Maarif, Pancasila harus menjadi “laku”, yakni perbuatan para elite dan warga.
Sedangkan menurut Romo Magnis Suseno, Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Pancasila selaras dengan agama dan kebudayaan yang hidup di Indonesia, sehingga mempertentangkannya satu sama lain justru bertentengan dan merupakan pengingkaran atas kepribadian dan sejarah bangsa Indonesia.
Karenanya Pancasila tidak cukup dipidatokan serta dijadikan slogan dan retorika semata, tetapi niscaya diwujudkan di dunia nyata dalam nilai dan praktik hidup bangsa Indonesia.
Transformasi nilai dan mentalitas keagamaan
Menurut Mukti Ali (1981), agama sebagai refleksi iman harus terbuka tidak hanya dalam ucapan, keyakinan, dan iman saja; tetapi agama juga merefleksikan sejauh mana iman itu diungkapk dalam kehidupan di dunia.
Agama berfungsi sebagai faktor motivatif, kreatif, sublimatif, liberatif, dan integratif dalam diri para pemeluknya di tengah kehidupan yang dijalaninya.
Karenanya agama dan cara menyiarkan agama sangat tidak memadai manakala dikomodifikasikan menja serba-entertainment, yang mendangkalkan pesan-pesan keagamaan substantif dan diganti dengan pesan-pesan hiburan yang artifisial di ruang publik.
Transformasi nilai kebudayaan Adiluhung
Sri Sultan Hamengku Buwono X: Renaisans Kebudayaan, yakni “pembangkitan kembali budaya lama digunakan sebagai strategi kebudayaan untuk membangun peradaban baru”.
Transformasi mentalitas dan kebudayaan Indonesia juga meniscayakan aktualisasi nilai-nilai kebudayaan yang hidup dalam sistem sosial masyarakat di negeri ini, antara lain sebagaimana ditampilkan eksemplarnya oleh jejak hidup dan perjuangan Sri Sultan Hamengku Buwono IX serta peran Keraton Yogyakarta Hadiningrat, yang menghadirkan kebudayaan adiluhung.
Dalam strategi kebudayaan yang berwawasan renaisans tersebut diperlukan “revolusi kultural” yang menyentuh aspek dan proses “soft side of change” untuk mengubah mindset dan perilaku.
Pendekatan kultural tersebut diperlukan guna mengubah proses yang bersifat “hard side of change” seperti perubahan pada aspek kelembagaan, sistem, dan prosedur yang lebih mudah diidentifikasi. Menurut Sri Sultan Hamengku Bowono X, para pihak yang menjadi “pemomong dan peneladan harus bisa berani mengubah cara berpikir dan bertindak dengan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya adiluhung agar menjadi perilaku warga.
Ditambah penyelenggara negara yang bekerja keras dan berpikir cerdas, akademisi yang kreatif dengan komitmen, rohaniwan yang mengamalkan kesalehan ritual dan kesalehan publik, wirausahawan yang inovatif dan berani mengambil resiko, didukung oleh warga yang kreatif.”
Demikianlah falsafah sekaligus transformasi mentalitas dan kebudayaan adiluhung Indonesia sebagaimana dasar nilai dan pesan penting dari Sultan Hamengku Buwono X serta menemukan role-model yang kuat pada figur Sri Sult Hamengku Buwono IX.
Sejalan dengan strategi kebudayaan yang multidimensi dan multiperspektif itulah maka dapat dirancang-bangun mentalitas dan kebudayaan adiluhung yang berbasis pada nilai iman-taqwa, akhlak mulia, dan kebudayaan luhur.
Hal ini sebagaimana terkandung dalam Pasal 31 15 UUD 1945 menuju peradaban Indonesia yang dicita-citakan para pendiri negara yakni perikehidupan kebangsaan yang (benar-benar) merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur di bumi nyata Indonesia dalam martabat luhur (adiluhung) berpondasikan nilai Pancasila, agama, dan khazanah kebudayaan bangsa!