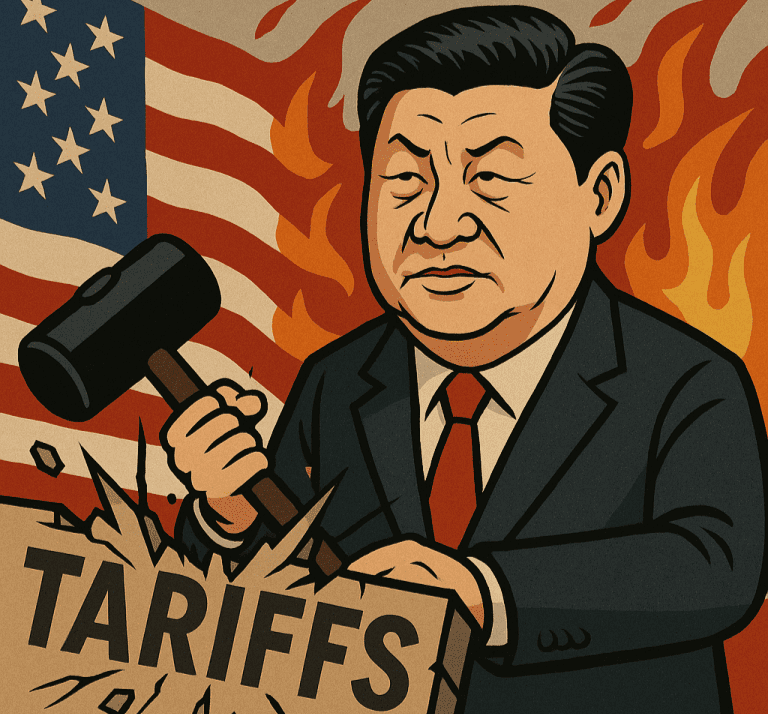MAKLUMAT — Dua negara adikuasa dunia—Amerika Serikat dan China—merupakan ekonomi terbesar sekaligus saling terkait erat. Namun, keduanya kini tampak lebih dekat menuju perpecahan ekonomi total. Perang dagang yang terus memanas mencapai titik baru bulan ini. Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif dasar atas impor dari China menjadi 145%.
Di sisi lain, Presiden China Xi Jinping tidak tinggal diam. Ia merespons dengan strategi penuh perhitungan. Di dalam negeri, perang dagang digambarkan sebagai bentuk perlawanan terhadap intimidasi Barat, ujian terhadap tekad nasional, dan pertempuran yang hanya bisa dimenangkan oleh Partai Komunis. Bagi Xi, ini adalah salah satu tantangan politik terbesar sejak pandemi COVID-19 melanda.
Namun, alih-alih sekadar bertahan, Xi memanfaatkan momen ini untuk memperkuat cengkeramannya atas kekuasaan. Dalam lawatan diplomatik terbarunya ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja, ia menyampaikan visi China sebagai kekuatan regional yang bertanggung jawab—berkomitmen menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global. Ia menyuarakan penolakan terhadap unilateralisme dan proteksionisme, serta menyerukan solidaritas Asia sebagai satu keluarga besar.
Namun, di balik retorika optimistis itu, ekonomi China sedang menghadapi tekanan berat. Industri yang bergantung pada ekspor terguncang akibat tarif tinggi, sementara konsumsi dalam negeri melemah. Krisis properti, lonjakan pengangguran muda, dan utang pemerintah yang membengkak turut memperumit situasi.
Meskipun demikian, ancaman terhadap Partai Komunis belum serius. Xi telah mengkonsolidasikan kekuasaannya dan kini menjadi pemimpin terkuat sejak Mao Zedong. Pemerintah tetap menjaga kontrak sosialnya: stabilitas dan kemakmuran ekonomi sebagai ganti pemerintahan otoriter.
Tapi jika perang dagang berkepanjangan dan menyebabkan kemerosotan ekonomi yang dalam, potensi ketidakpuasan publik bisa meningkat. Itulah celah yang berpotensi menjadi titik lemah dalam sistem kekuasaan Xi.
Dalam wawancara dengan DW, Selasa (22/4), pakar China, Clifford Kunin menjelaskan bagaimana perang dagang ini telah dijadikan alat politik oleh Xi. Partai Komunis tumbuh dari semangat revolusi dan perlawanan—dan mereka ahli dalam memobilisasi rakyat melalui propaganda nasionalis. Perang dagang digambarkan sebagai perjuangan heroik melawan kekuatan Barat, yang membangkitkan solidaritas rakyat.
Selain itu, Xi juga melancarkan “serangan pesona” dengan meningkatkan kerja sama regional, terutama di Asia Tenggara. Kunjungan ke negara-negara seperti Vietnam menjadi sinyal bahwa Beijing ingin membentuk “front Asia” sebagai penyeimbang terhadap dominasi AS. Namun, banyak negara di kawasan itu juga memiliki ketergantungan ekonomi terhadap Amerika, sehingga strategi Xi bisa menghadapi tantangan serius.
Di sisi lain, kerugian akibat perang dagang tidak sepenuhnya sepihak. Contohnya, China baru-baru ini mengembalikan pesawat Boeing 737 yang telah mereka beli—bukan karena politis, tapi karena beban tarif membuatnya tak lagi terjangkau. Di satu sisi, ini dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan Tiongkok. Namun di sisi lain, negara itu tetap membutuhkan teknologi dan komponen buatan AS untuk menopang industri dan pertahanan mereka.
Kesimpulannya, Xi Jinping sedang berjudi. Ia menggunakan konflik ini untuk memperkuat legitimasi politik dan nasionalisme, tapi di saat yang sama menghadapi risiko ekonomi yang besar. Jika konsumen tidak membelanjakan uang dan ekspor terus merosot, tekanan internal bisa semakin berat.
Bagaimana China akan keluar dari pusaran ini? Itu pertanyaan besar yang akan menentukan masa depan Xi Jinping—dan mungkin, masa depan tatanan ekonomi dunia.***