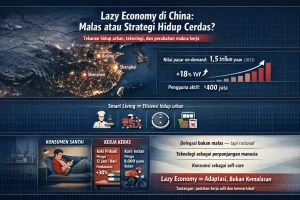MAKLUMAT — Semenjak Muhammadiyah berdiri, pembanteras si buta-huruf pun terus berlaku juga. Meluap di kalangan kaum putera dan puteri, tua muda, desa dan kota, kaya dan miskin, sehingga orang yang tidak kita kira-kirakan dapat membaca, mereka ada pandai membaca (Keputusan Kongres Muhammadiyah XXVI tahun 1937).
Pandangan sejarah kota dari kitab klasik Ibnu Khaldun dan Al Farabi dapat ikut memberi warna penting dalam memahami bagaimana kota harus berfungsi.
Ibnu Khaldun menempatkan kota sebagai pusat interaksi sosial dan ekonomi yang membawa kemajuan, namun harus diatur dengan keadilan agar tidak menimbulkan eksploitasi dan kerusakan. Sementara Al Farabi menekankan kota sebagai komunitas politik yang ideal bertujuan mewujudkan kebahagiaan bersama melalui tata kelola adil dan kolektif. Prinsip-prinsip ini relevan untuk mengingatkan bahwa kota tidak boleh hanya menjadi panggung pertarungan kekuasaan dan modal, melainkan ruang untuk kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh warga.
Dalam perjalanan sejarah perjuangan sosial di Indonesia, literasi telah menjadi lebih dari sekadar kemampuan membaca dan menulis. Ia merupakan gerakan transformasi sosial yang mengangkat martabat rakyat, memperluas ruang partisipasi warga, dan membuka akses kesetaraan. Seperti yang dicontohkan oleh Muhammadiyah dalam Kongres XXVI tahun 1937, pemberantasan buta huruf bukan hanya upaya pendidikan, melainkan gerakan inklusif lintas gender, usia, kelas sosial, dan wilayah.
Muhammadiyah menempatkan literasi sebagai hak yang wajib diterima semua orang, bukan privilese segelintir elite. Ini adalah praktik egalitarianisme di lapangan yang mengembalikan martabat kaum miskin dan desa serta membangun ruang partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan keagamaan.
Sejalan dengan ini, Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah menegaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah fondasi peradaban dan keadilan sosial. Ia menempatkan perpustakaan dan majelis ilmu sebagai ruang publik yang harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi kelas. Ibnu Khaldun melihat ilmu sebagai alat mobilitas sosial sekaligus pengontrol elite yang korup, sehingga kota sebagai pusat ‘umran (peradaban) menjadi tempat yang harus menjamin akses pengetahuan untuk keadilan. Dalam kerangka ini, perjuangan warga untuk mendapatkan akses terhadap ilmu, partisipasi dalam tata kelola, dan melawan monopoli elite atas sumber daya menjadi esensial.
Mengklaim Kembali Hak Warga atas Kota untuk Keadilan Sosio-Ekologis
Di Indonesia sekarang, sehari-hari kita sedang menghadapi gelombang demonstrasi yang sesungguhnya mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin keadilan sosial-ekologis bagi warganya. Permasalahan ketimpangan yang menganga, sistem perpajakan yang timpang, serta dominasi oligarki dalam menguasai sumber daya ekonomi dan ruang perkotaan menjadi pangkal dari krisis multidimensi ini.
Tak hanya mengancam kesejahteraan masyarakat, krisis ini juga menghasilkan kerusakan lingkungan dan penyempitan ruang demokrasi, menciptakan situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi masa depan kota-kota kita.
Dalam situasi seperti ini, konsep Right to the City dari David Harvey menjadi sangat penting sebagai kerangka perjuangan. Harvey mengembangkan gagasan ini bukan hanya sebagai hak individu atas ruang fisik, tetapi sebagai hak kolektif warga untuk merebut kembali pengendalian atas proses produksi ruang kota yang selama ini didominasi oleh kepentingan modal. Hak ini bukan sekadar akses, tetapi keterlibatan aktif warga dalam mengatur dan mengubah kota mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan keadilan sosial-ekologis.
Ketimpangan yang kian melebar memperlihatkan bahwa kota-kota di Indonesia hari ini telah berubah menjadi arena eksklusif bagi kelompok elite yang mengontrol modal dan kekuasaan politik. Warga, terutama yang berpenghasilan rendah, terpinggirkan dan kehilangan haknya atas ruang hidup yang layak dan bermartabat. Gelombang protes yang tengah berlangsung sejatinya adalah manifestasi nyata dari upaya warga merebut kembali hak mereka atas kota sebagai tempat hidup bersama yang adil dan berkelanjutan.
Mengembalikan hak warga atas kota berarti memperkuat partisipasi bermakna dalam perencanaan dan pengelolaan kota, memastikan proses demokrasi yang inklusif, sekaligus membangun solidaritas sosial lintas sektor untuk menuntut kebijakan yang berpihak pada rakyat banyak.
Saatnya warga kota mempelajari kembali kotanya, kota yang bukan sekadar menjadi arena bagi akumulasi modal dan penguasaan segelintir elite, melainkan ruang demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan merebut kembali hak atas kota, kita membuka peluang bagi transformasi sosial-ekologis yang membebaskan dan memanusiakan kota-kota kita. Al Farabi, dalam Kota Utama menyebutkan kota untuk mewujudkan kebahagian bersama melalui tata kola yang adil dan koletif.
_____________
*) Artikel ini sudah pernah dipublikasikan di laman resmi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah dengan judul “Dari Literasi ke Lanskap Keadilan Sosio-Ekologis”.