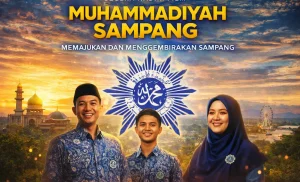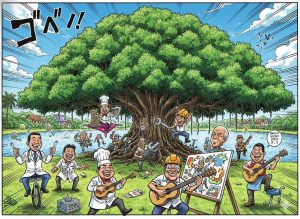MAKLUMAT – Sejarah sering kali bukan sekadar deretan tanggal dan nama, melainkan ruang gema bagi kenangan yang enggan usai. Ketika pemerintah kembali menggulirkan wacana untuk menobatkan Soeharto sebagai pahlawan nasional, seolah lembaran lama yang belum selesai tiba-tiba dibuka lagi. Di balik tinta yang mengering, masih ada noda yang tak mudah dihapus.
Dalam ruang publik yang gaduh, dua arus besar pemikiran saling berpapasan. Dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, muncul suara-suara yang berlawanan. Sebagian menolak dengan tegas, sebagian lain menyambut dengan alasan jasa dan pembangunan.
Sejarah pun kembali menuntut kita memilih: hendak mengenang Soeharto sebagai bapak pembangunan, atau mengingatnya sebagai penguasa yang pernah menanam luka di dada bangsa.
Menolak Lupa: Suara dari Nurani
KH Ahmad Mustofa Bisri, atau yang akrab dipanggil Gus Mus, berdiri di antara kenangan itu. “Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan pahlawan nasional.” Kalimat sederhana, tapi mengandung gema panjang dari masa lalu -masa ketika suara ulama dibungkam, dan kebebasan dijaga oleh ketakutan.
Usman Hamid dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah menambahkan nada yang sama. Baginya, pahlawan tak seharusnya lahir dari kisah yang tak tuntas, dari nama yang masih dibayangi gugatan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi.
Pahlawan, kata mereka, adalah mereka yang bersih dari noda, yang perjuangannya tidak menimbulkan air mata di mata rakyat.
Pemikiran mereka seakan menyatu dengan pesan lama dari Sutan Takdir Alisjahbana dalam Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru (1948): “Kepahlawanan sejati bukan hanya keberanian melawan musuh, melainkan kesetiaan terhadap nilai-nilai yang mempertinggi martabat manusia.”
Dalam kalimat itu, pahlawan bukan sekadar mereka yang menang, tetapi yang tetap setia pada nurani bahkan ketika dunia berbalik arah.
Logika Pengakuan Jasa
Namun, sejarah tak pernah hitam putih. Ada pula suara yang menuntut keadilan bagi jasa-jasa Soeharto. Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menyebut Soeharto sebagai sosok yang berjasa besar sejak revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan. Ia memimpin negeri ini melewati badai politik, menumbuhkan sawah-sawah dengan swasembada, dan menghadirkan stabilitas yang lama dirindukan.
Bagi sebagian orang, jasa-jasa itu adalah batu pijakan. Mereka melihat Soeharto bukan dari dosa kekuasaan, tapi dari buah keberhasilannya. Pembangunan dipandang sebagai bentuk kepahlawanan; stabilitas dianggap bagian dari pengabdian.
Namun seperti diingatkan Franz Magnis Suseno dalam Etika Politik (1988),
“Seorang pemimpin hanya layak disebut pahlawan bila tindakannya mengabdi kepada kemanusiaan dan keadilan, bukan kepada kekuasaan.”
Maka, jasa besar tanpa keadilan adalah menara tinggi yang dibangun di atas tanah retak. Ia megah, tapi takkan bertahan lama.
Di Antara Cahaya dan Bayangan
Bangsa ini berdiri di antara dua kutub: antara rasa syukur atas kemajuan dan rasa perih atas penindasan. Soeharto adalah cermin besar tempat kita menatap diri sendiri—melihat keberhasilan dan kesalahan, kemajuan dan kejatuhan, sekaligus.
Sejarawan Taufik Abdullah pernah menulis dalam Indonesia: Towards Democracy (2009):
“Pahlawan adalah mereka yang memberi inspirasi moral bagi bangsa, bukan sekadar mereka yang memimpin dengan hasil besar.”
Kutipan itu seperti menuntun kita pada satu renungan: kepahlawanan adalah soal teladan, bukan semata prestasi.
Ingatan yang Tak Padam
Bung Karno, dalam Di Bawah Bendera Revolusi (1959), pernah menulis, “Pahlawan sejati ialah mereka yang berjuang bukan untuk dikenang, tetapi untuk menegakkan kemanusiaan.”
Dan di situlah letak ujian terbesar bangsa ini: berani mengingat tanpa dendam, tapi juga tak mudah memberi maaf pada kekuasaan yang menyisakan luka.
Mungkin bangsa ini belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya. Kita masih belajar membedakan antara jasa dan dosa, antara pembangunan dan penindasan, antara kenangan dan pengampunan.
Soeharto, dalam ingatan kolektif bangsa ini, bukan hanya nama di lembar sejarah. Ia adalah persimpangan: tempat kita menimbang arti pahlawan, menakar harga kemanusiaan, dan menulis ulang definisi tentang keadilan.
Dan mungkin, sebelum gelar pahlawan diberikan, bangsa ini perlu menjawab satu pertanyaan yang paling sederhana, namun paling berat: apakah kita sudah benar-benar sembuh dari luka yang ditinggalkannya?