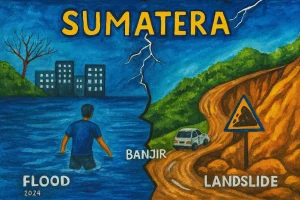MAKLUMAT – Ada pagi-pagi tertentu di kota ketika udara terasa lebih kosong dari biasanya. Jalanan belum benar-benar ramai, langit belum sepenuhnya biru, namun kita merasakan kesunyian yang tidak mudah dijelaskan. Kesunyian yang bukan berasal dari kurangnya suara, melainkan ketiadaan percakapan. Kota seperti menarik napas pelan, seolah menyimpan sesuatu yang hilang dari dadanya sendiri.
Di banyak kota di Jawa Timur, kesunyian semacam itu mulai sering muncul. Surabaya yang tegas, Malang yang lembut, Jember yang pelan, Kediri yang bertumbuh dan semuanya berjalan cepat, namun justru meninggalkan semacam kekosongan sentimental di tengah kedewasaannya. Kita menyaksikan pertumbuhan, pembangunan, dan perubahan, tetapi jarang merasa ikut berada di dalam denyutnya.
Kota-kota ini hidup, tapi entah mengapa terasa kurang hadir. Seperti ada jarak tipis antara warganya dengan ruang yang mereka diami. Seperti ada jiwa publik yang pergi dari sebuah rumah yang masih berdiri.
Kita pun merasa seperti sedang berjalan di dalam museum yang lampunya dipadamkan lebih cepat dari biasanya. Jalan-jalannya ramai, trotoarnya padat, pusat perbelanjaan menyalakan lagu-lagu yang sama setiap minggu. Namun di tengah keramaian itu, ada sesuatu yang diam-diam hilang yakni jiwa publik. Suatu ruang batin bersama yang dulu menjadi alasan mengapa manusia ingin hidup berdekatan, alih-alih hanya saling melintas sebagai bayangan.
Di masa lampau, kota adalah panggung percakapan. Orang tidak hanya bertemu, mereka saling mengenali. Ada cerita yang tumpah di warung kopi, ada perdebatan yang menggema di balai kota, ada kabar yang menetes dari pasar ke pasar, membentuk komunitas. Kini, ruang-ruang itu menyusut.
Warung kopi bergeser menjadi kafe-kafe senyap, tempat manusia duduk berdekatan tetapi hidup di layar masing-masing. Balai kota berubah menjadi gedung administratif yang hanya didatangi untuk urusan yang terpaksa. Pasar kehilangan suaranya ketika masyarakat lebih percaya pada keranjang belanja online yang tiba tanpa menyapa.
Di titik ini, kita melihat betapa sebuah kota bisa terus tumbuh tanpa benar-benar hidup. Ia bisa memiliki gedung yang tinggi, jalan yang lebar, tetapi tidak punya percakapan. Tidak punya denyut batin yang dibentuk oleh perjumpaan.
Sebuah kota, agar benar-benar menjadi kota, membutuhkan ruang bagi warganya untuk hadir dan dilihat, untuk saling memaknai. Tanpa itu, kota hanya menjadi “tempat bermukim” seperti terminal besar bagi orang-orang yang selalu hendak bergegas pergi.

Dan di tengah keretakan itu, hadir sesuatu yang semula kita anggap sekadar hiburan yakni aliran informasi. Televisi, radio, dan kini media sosial menjadi ruang publik baru yang lebih luas, tetapi juga lebih tipis. Ruang yang memungkinkan suara dari ujung Madura bertemu dengan suara dari kaki Semeru. Namun, ruang itu bukan tanpa harga.
Di kota-kota yang sibuk, sering kali informasi tidak lagi menjadi perekat, tetapi justru pemecah. Fragmentasi itu tampak jelas dalam bagaimana layar-layar digital kita bekerja. Kita melihat setiap warga hidup dalam gelembung algoritmanya sendiri. Ruang publik yang seharusnya memungkinkan perdebatan justru berubah menjadi lorong-lorong sempit tempat orang hanya mendengar apa yang ingin ia dengar.
Di Surabaya, misalnya, riuh debat publik kini lebih sering lahir di ruang digital yang penuh amarah. Di Malang, isu-isu kota dibicarakan lebih ramai di kolom komentar daripada forum warga. Di Kediri, rumor dapat menumpuk lebih cepat daripada klarifikasi. Kita seperti hidup berdampingan, tetapi tidak pernah benar-benar berbicara. Kota kehilangan jiwa publiknya ketika warganya berhenti saling mendengarkan.
Ada satu pergeseran yang turut memperdalam kehilangan itu yakni semakin langkanya ruang yang memberi peluang bagi warga untuk menafsir makna hidup bersama. Penyiaran, sebagai jantung informasi publik, semestinya hadir untuk menjadi jembatan, bukan sekadar juru siar peristiwa. Namun kita melihat, terutama di kota-kota Jawa Timur, bagaimana media kerap terseret arus cepat sensasi, kehilangan ketenangannya untuk mendengar apa yang tidak tampak di permukaan.
Liputan tentang kota banyak berhenti pada bangunan baru, kebijakan terbaru, atau acara seremonial. Jarang sekali media bertanya bagaimana warga merasakan kotanya? Bagaimana suara pedagang sayur di Pasar Keputran, nelayan di Muncar, ibu-ibu yang menunggu di puskesmas Kalianget, atau anak-anak yang bermain di pinggir bengawan Bojonegoro? Di mana suara mereka dalam siaran kita? Ketika suara warga hilang, kota ikut kehilangan nadinya.
Namun, kehilangan jiwa publik bukanlah kematian. Ia lebih mirip hibernasi, sebuah tidur panjang yang masih menyimpan kemungkinan untuk bangun. Kota yang kehilangan pusat batinnya masih bisa pulih jika menemukan kembali ruang-ruang perjumpaan itu. Sebuah ruang yang tidak terlalu lantang, tetapi cukup lapang bagi percakapan sederhana.
Di banyak titik Jatim, kita melihat embrio itu muncul. Radio komunitas di desa-desa yang kembali memutar cerita warga. Program televisi lokal yang perlahan mengangkat kisah-kisah masyarakat pinggiran. Forum warga yang kembali hidup di beberapa kampung kota. Media digital yang mulai menginisiasi ruang dialog antargenerasi.
Tugas kita adalah memastikan ruang-ruang itu tidak padam. Sebab di situlah kota menemukan kembali jati dirinya, bukan melalui beton dan cahaya, tetapi melalui percakapan dan keberanian untuk hadir bersama. Tugas penyiaran, dalam hal ini, jauh lebih mulia daripada sekadar menyiarkan. Ia memanggil warga untuk kembali menjadi publik.
Pada akhirnya, kota adalah rumah bagi ingatan. Dan ingatan tidak pernah tercipta dari gedung yang megah, melainkan dari perjumpaan, dari percakapan di teras, dari sapaan yang tulus di pasar, dari berita yang disampaikan dengan jernih, dari ruang yang membuat orang merasa dilihat.
Jika kota-kota Jawa Timur ingin tumbuh tanpa kehilangan dirinya, mereka harus merawat kembali apa yang dulu paling sederhana yakni kebersamaan. Ruang publik yang tidak hanya terlihat di peta, tetapi terasa di hati warganya. Sebab kota yang kehilangan jiwa publik hanyalah kumpulan bangunan yang berdiri, tanpa arah batin yang memandu.
Dan barangkali, tugas penyiaran hari ini adalah menghidupkan kembali apa yang perlahan padam itu, mengembalikan suara kota kepada warganya. Sebab hanya ketika suara-suara itu bertemu, kota benar-benar hidup. Panjang umur kehidupan!