Gelombang demonstrasi yang terjadi pada 25-28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR RI telah memicu respons politik yang signifikan. Lima anggota DPR RI dari berbagai partai yakni Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya), Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Adies Kadir, secara berturut-turut dinonaktifkan oleh partai politik mereka masing-masing.
Keputusan ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang legitimasi hukum, efektivitas sanksi politik, dan implikasinya terhadap demokrasi perwakilan di Indonesia.
Demonstrasi dimulai pada 25 Agustus 2025 dengan aksi mahasiswa yang menuntut percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Aksi ini kemudian berkembang menjadi protes yang lebih luas terkait kenaikan tunjangan anggota DPR RI di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
Puncak demonstrasi terjadi pada 28 Agustus 2025, ketika ribuan demonstran yang terdiri dari buruh dan mahasiswa turun ke jalan. Aksi yang awalnya kondusif berubah menjadi ricuh pada malam hari, dengan sejumlah insiden termasuk pelemparan bambu runcing dan pembakaran sampah.
Polisi mengidentifikasi adanya penyusup yang memicu kericuhan tersebut. Adalah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, meninggal dunia akibat ditabrak dan dilindas oleh kendaraan taktis milik Satuan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Metro Jaya pada saat unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI.
Kericuhan yang menyebabkan korban luka dan akhirnya memakan korban jiwa ini bukan sekadar tragedi personal, melainkan simbol dari rapuhnya komunikasi publik antara pemerintah, DPR, dan rakyat.
Kematian Affan Kurniawan memperparah krisis kepercayaan publik. Demonstrasi yang berawal dari aspirasi konstitusional rakyat justru berujung pada hilangnya nyawa.
Situasi ini menunjukkan kegagalan negara dalam memastikan ruang demokratis yang aman serta kegagalan DPR dalam menjaga citra lembaga legislatif sebagai rumah rakyat.
Merespons tekanan publik pasca demonstrasi, berbagai partai politik mengambil langkah tegas yaitu Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach pada 31 Agustus 2025 disusul dengan Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya pada tanggal yang sama dan Partai Golkar selanjutnya menonaktifkan Adies Kadir pada 1 September 2025.
Alasan yang dikemukakan adalah pernyataan dan tindakan yang dinilai “mencederai perasaan rakyat” serta melanggar etika parlemen. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019, tidak terdapat istilah “penonaktifan” anggota DPR. Undang-undang hanya mengenal mekanisme pemberhentian melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana diatur dalam Pasal 239 UU MD3.
Penonaktifan yang dilakukan partai politik memiliki karakteristik sebagai berikut:
-Sifat Internal Partai: Keputusan penonaktifan hanya berlaku secara internal di fraksi masing-masing
-Bukan Pemberhentian Formal: Tidak mengubah status keanggotaan DPR secara hukum
-Pemberhentian Sementara: Anggota yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangan sebagai wakil rakyat
-Hak Finansial Tetap Berlaku: Masih berhak menerima gaji dan tunjangan karena status keanggotaan DPR masih sah
Untuk pemberhentian formal anggota DPR, harus melalui proses PAW yang melibatkan:
-Usulan dari partai politik
-Persetujuan Pimpinan DPR
-Penetapan oleh Presiden
Proses ini memastikan pemberhentian dilakukan sesuai koridor hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Di satu sisi, penonaktifan anggota DPR oleh partai politik tampak sebagai respons cepat terhadap tekanan publik. Namun, langkah ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) hanya mengenal mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), bukan “penonaktifan.”
Akibatnya, anggota yang dinonaktifkan masih berhak menerima hak finansial meskipun tidak menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Kondisi ini menimbulkan paradoks: rakyat marah karena merasa dikhianati, sementara para politisi tetap memperoleh keuntungan finansial.
Beberapa pakar hukum tata negara menilai penonaktifan ini sebagai “manuver politik” yang tidak memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Mereka berpendapat bahwa langkah ini lebih merupakan upaya partai untuk merespons tekanan publik daripada tindakan hukum yang substantif.
Kritik utama adalah ketiadaan dasar hukum yang kuat untuk penonaktifan, yang berpotensi menciptakan preseden yang problematik dalam sistem parlemen Indonesia.
MKD telah menyoroti pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota DPR tersebut, termasuk pernyataan yang dinilai tidak pantas dan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat wakil rakyat. Namun, sanksi MKD memiliki keterbatasan dalam hal pemberhentian definitif anggota DPR.
Penonaktifan ini mencerminkan dilema antara responsivitas partai politik terhadap tuntutan publik dengan kebutuhan stabilitas kelembagaan. Di satu sisi, partai menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi masyarakat. Di sisi lain, hal ini dapat menciptakan preseden di mana tekanan massa dapat mempengaruhi komposisi parlemen tanpa melalui mekanisme hukum yang tepat.
Dari perspektif efektivitas, penonaktifan tanpa konsekuensi finansial dapat dipandang sebagai sanksi yang tidak memadai. Anggota DPR yang dinonaktifkan tetap menerima seluruh hak finansial mereka, sementara tidak menjalankan kewajiban sebagai wakil rakyat.
Penonaktifan lima anggota DPR secara bersamaan juga menimbulkan pertanyaan tentang representasi politik. Konstituennya secara de facto kehilangan perwakilan aktif di parlemen, meskipun secara formal kursi mereka masih terisi.
Kasus ini mengungkap kebutuhan mendesak untuk merevisi UU MD3 agar mencakup mekanisme sanksi yang lebih gradual dan proporsional. Selain pemberhentian permanen melalui PAW, perlu dipertimbangkan sanksi intermediate seperti:
-Pemberhentian sementara dengan prosedur yang jelas
-Pemotongan hak finansial untuk pelanggaran tertentu
-Mekanisme evaluasi dan rehabilitasi
Mahkamah Kehormatan Dewan perlu diperkuat dengan kewenangan yang lebih luas dan sanksi yang lebih bervariasi. Hal ini akan memungkinkan penanganan pelanggaran etika yang lebih proporsional dan efektif.
Partai politik perlu lebih transparan dalam menjelaskan dasar dan mekanisme penonaktifan anggota mereka. Publik berhak mengetahui kriteria dan prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut.
Penonaktifan lima anggota DPR RI pasca demonstrasi 25-28 Agustus 2025 menunjukkan ketegangan antara tuntutan akuntabilitas politik dan keterbatasan kerangka hukum yang ada. Meskipun partai politik menunjukkan responsivitas terhadap kritik publik, langkah ini mengungkap kelemahan sistemik dalam mekanisme sanksi parlemen Indonesia.
Ke depan, diperlukan reformasi komprehensif terhadap sistem sanksi dan akuntabilitas anggota parlemen. Hal ini tidak hanya untuk memastikan efektivitas sanksi, tetapi juga untuk menjaga integritas dan legitimasi lembaga legislatif sebagai pilar demokrasi.
Kasus ini menjadi momentum penting untuk evaluasi mendalam terhadap sistem parlemen Indonesia, khususnya dalam hal keseimbangan antara kebebasan berpendapat anggota DPR dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Tanpa reformasi yang tepat, risiko politisasi sanksi dan ketidakpastian hukum akan terus mengancam stabilitas sistem demokrasi Indonesia.
Masukan dan Kritik bagi Pemerintah:
Perkuat komunikasi publik: Pemerintah perlu hadir dengan penjelasan yang transparan, bukan reaktif dan defensif. Kematian Affan adalah alarm bahwa masyarakat tidak lagi percaya pada narasi resmi.
Tangani aparat yang represif: Evaluasi dan penindakan tegas terhadap aparat yang terbukti melakukan kekerasan dalam demonstrasi harus dilakukan. Tanpa langkah ini, komitmen terhadap demokrasi akan dipertanyakan.
Respons krisis ekonomi dengan kebijakan nyata: Rakyat menolak kenaikan tunjangan DPR bukan sekadar karena nominal, tetapi karena ketimpangan antara kesejahteraan pejabat dan penderitaan masyarakat.
Masukan dan Kritik bagi DPR RI:
Revisi UU MD3: DPR perlu membuka ruang pembahasan revisi mekanisme sanksi internal, termasuk opsi pemberhentian sementara yang berdampak pada hak finansial, bukan sekadar formalitas politik.
Bangun budaya etika politik: Pernyataan dan tindakan anggota DPR harus mencerminkan empati dan tanggung jawab. Pernyataan yang melukai hati rakyat tidak bisa hanya diselesaikan dengan “penonaktifan” semu.
Dengar aspirasi rakyat secara aktif: Demonstrasi yang berujung ricuh adalah cerminan bahwa mekanisme representasi politik tidak berjalan. DPR harus memperkuat fungsi reses, dialog publik, dan kanal aspirasi yang terbuka.
Kasus penonaktifan lima anggota DPR RI, ditambah dengan tragedi kematian Affan Kurniawan, adalah cermin krisis akuntabilitas politik di Indonesia. Ketika rakyat merasa dikhianati, protes tidak hanya berubah menjadi kericuhan, tetapi juga melahirkan korban jiwa. Situasi ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan refleksi mendalam: apakah mereka masih menjadi representasi sejati rakyat, atau sekadar mempertahankan kepentingan elit politik? (*)

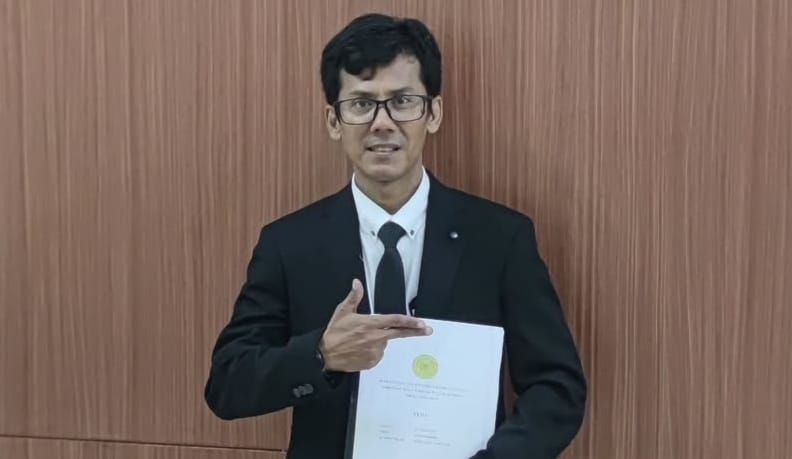






Comments