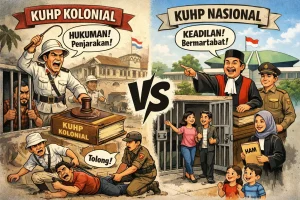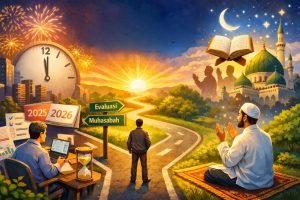MAKLUMAT — Gerakan reformasi pada awalnya adalah gerakan moral yang berusaha untuk melakukan proses demokratisasi tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah demokratisasi merujuk pada usaha mendekatkan kekuasaan pada kebutuhan dan kepentingan rakyat.
Demokratisasi dalam konteks reformasi adalah upaya meluruskan konstruksi hukum dan ketatanegaraan yang dipraktikkan oleh rezim Orde Baru. Kritik tajam atas orde baru adalah pola manajerial kekuasaan yang dijalankan secara otoriter, koruptif dan kapitalistik.

Dalam konteks ini, demokratisasi adalah langkah untuk menyelamatkan bangsa dari keterpurukan di segala bidang akibat tata kelola pemerintahan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD RI 1945. Problem reformasi sejatinya ada pada fragmentasi kepentingan yang berada di dalamnya. Ragam kepentingan dan motivasi, baik yang bersifat ideologis maupun kepentingan politik internasional berada di dalamnya. Ragam kepentingan kemudian bertarung untuk menghegemoni rekonstruksi kehidupan berbangsa-bernegara era reformasi.
Mahasiswa dan CSO yang menjadi motor penggerak reformasi memiliki latar ideologi yang beragam. Dan ketika mereka bergerak tentunya memiliki kepentingan untuk mewujudkan idealism yang mereka pahami. Di satu sisi, kekuatan internasional juga memiliki kepentingan atas jatuhnya orde baru.
Kepentingan itu berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam dan pasar domestik yang prospektif. Problemnya, kepentingan yang mendominasi pembangunan sistem hukum dan kenegaraan pasca reformasi adalah kelompok yang secara ideologis bersinergi dengan pemodal (neoliberalism-MNC).
Salah satu anomali yang sampai hari ini dianggap sebagai kelumrahan adalah masih dianutnya rezim pertumbuhan ekonomi dan developmentalism dalam skema pengelolaan negara. Konsep ekonomi kapitalistik yang meletakkan pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur kemakmuran dan kesejahteraan, pada masa reformasi ini masih diterapkan. Padahal, konsep itu dianggap sebagai biang dari kegagalan ekonomi dan ketimpangan sosial.
Hal senada juga terjadi pada konsep pembangunan kita hari ini yang berhaluan developmentalism, meletakkan takaran keberhasilan pemerintahan dan tingkat kemajuan masyarakat pada capaian bangunan fisik. Menjadi lumrah ketika kampanye Pilpres 2024, bangsa ini banyak disibukkan dengan isu prosentase pertumbuhan ekonomi, panjang ruas jalan tol dan kuantitas insfrastruktur yang dibangun.
Permasalahan pelik yang hadir dalam sistem hukum indonesia pasca reformasi bermuara pada amandemen konstitusi 1945. Konstitusi secara teoritis adalah kesepakatan bersama warga negara tentang cita kebangsaan dan konstruksi dasar kebernegaraannya.
Perubahan konstitusi berarti perubahan kesepakatan bangsa ini tentang cita dan konstruksi berbangsa-bernegaranya. Namun, yang menarik dari amandemen UUD RI 1945 ada pada limitasi atas poin perubahan yang tidak boleh menyangkut pembukaan dan konsep Negara Kesatuan.
Pembatasan perubahan ini mengindikasikan adanya kesadaran bahwa sejauh manapun amandemen itu dilakukan, falsafah dan cita hidup bangsa yang disepakati dalam pembukaan UUD RI 1945 tidak boleh berubah. Tetapi, perubahan substansi hak menguasai negara, mekanisme pemilihan Presiden, dan akomodasi DUHAM dalam Pasal 28, secara esensial menggeser falsafah kebangsaan kita.
Amandemen yang seharusnya mempertegas dan memperjelas konstruksi filosofis berbangsa dan bernegara di Indonesia, dalam prakteknya malah menimbulkan berbagai kerancuan pada tataran paradigmatik.
Perubahan Corak dan Watak Demokrasi.
Pendiri bangsa ketika merumuskan Pancasila, menyepakati piagam Jakarta dan naskah konstitusi 1945, menegaskan bahwa Indonesia didirikan diatas konsep negara hukum bukan negara kekuasaan.
Bersamaan dengan itu pula disepakati bahwa konstruksi berhukum kita dilandasi falsafah permusyawaratan bukan individualism dan liberalism. Konsekuensi dari permusyawaratan adalah dasar penentuan suatu keputusan tidak pada besaran masa pendukung, tetapi pada kebijaksanaan dan kesepakatan bersama yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan dan kekeluargaan (persatuan).
Ketika amandemen konstitusi 1945 berbuah Pendegradasian kedudukan dan fungsi MPR diikuti skema Pilpres dan Pilkada langsung, terjadi perubahan kualitatif terhadap wajah demokrasi dan manajemen pemerintahan di pusat dan daerah. Pada aspek pengambilan keputusan dan pembuatan hukum, perubahan terlihat dari kian langkahnya permufakatan berdasar akal sehat dan moralitas. Sebagian besar keputusan dan hukum dihasilkan dari adu kekuatan masa dan proses tawar menawar kepentingan permodalan.
Perubahan pola pemilihan kepala pemerintahan pada level nasional maupun lokal dari sistem perwakilan oleh legislative ke sistem langsung tidak sepenuhnya berdampak positif bagi hadirnya pemimpin yang berkualitas. Di tingkat nasional, dua figur presiden terpilih dari skema pemilihan presiden langsung, ternyata tidak cukup baik untuk membawa Indonesia menjadi negara yang berkemajuan. Figur pertama bermasalah dengan isu korupsi di periode keduanya, sedangkan figur kedua malah berhasil meningkatkan rasio utang Indonesia, serta sensitive terhadap kritik.
Di tingkat daerah jauh lebih memprihatinkan. Provinsi Jawa Timur misalnya, hampir semua daerah bermasalah dengan korupsi yang dilakukan oleh Bupati dan Wali Kotanya. Paling baru, mantan Gubernur dua priode saat ini akrab dengan Gedung KPK.
Problem sistemik dari kegagalan Pilpres dan Pilkada langsung ada pada manuver pemilik modal ke dalam ruang kebijakan pemerintahan melalui pemenangan calon kepala daerah dan kepala desa. Infiltrasi kepentingan pemilik modal dalam tata kelola pemerintahan dan program pembangunan dimulai dari proses Pilkadal.
Dari proses itu, amandemen konstitusi 1945 nyatanya tidak memperkuat demokratisasi, tetapi malah mempromosikan plutokrasi. Tujuan reformasi untuk mendekatkan kekuasaan dan pemerintahan pada kehendak dan aspirasi rakyat, praktiknya malah mengalienasi kekuasaan dan pemerintahan pada sekelompok masyarakat pemilik modal.
Di tingkat nasional muncul fenomena Meikarta dan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Di tingkat Lokal Sidoarjo, muncul Perbup tentang Upah Minimum Khusus Pedesaan yang potensial memiskinkan, dan kebijakan perizinan industri yang tidak ramah lingkungan.
Pergeseran corak demokrasi di tingkat lokal kian memprihatinkan, karena praktik transaksional yang tadinya hanya membudaya di tingkatan pemilihan kepala desa, secara massive mewarnai konteks pemilihan pada level pilkada dan pemilu. Wajar jika pucuk pimpinan di lingkup daerah diisi oleh mereka yang bermodal, atau setidaknya oleh “perwakilan” pemilik modal.
Dari proses inilah kemudian muncul kebijakan yang destruktif terhadap lingkungan dan diskriminatif terhadap mayoritas masyarakat miskin dan rentan yang ada. Dalam kondisi demikian, ruang publik yang seharusnya menjadi harapan bagi proses penguatan kapasitas dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan kian terkikis.
Pengikisan ruang publik dilakukan secara terstruktur melalui penguasaan media dan intervensi berkedok penegakan hukum. Wajah asli demokrasi indonesia sebagai bentuk komunikasi organik bagi pewujudan cita bersama, berubah menjadi sekedar komunikasi mekanik yang bias kepentingan politik dan ekonomi.
Bias Nilai dalam Tradisi Berhukum.
Motivasi tertinggi dari perjuangan pendiri bangsa mewujudkan kemerdekaan adalah terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan beradab, serta memenuhi tuntutan izzul islam wa al-muslimin. Motivasi kemerdekaan itulah yang di kemudian hari memunculkan perdebatan sengit tentang substansi Pancasila dan bentuk sistem bernegara pada awal pembentukan konstitusi, serta beberapa perlawanan bersenjata di daerah.
Sebagai negara mayoritas muslim, ada kesadaran kolektif tentang kebutuhan sistemik untuk menyandarkan hukum dan tradisi berhukum pada nilai dan ajaran agama. Hal ini diletakkan sebagai bagian dari usaha menjalankan ajaran agama dan membentuk masyarakat utama yang adil dan Makmur. Asumsi dasarnya adalah, hukum yang terbaik adalah hukum Allah dan tidak akan ada keadilan dan kesejahteraan sejati tanpa kehadiran hukum Allah.
Hadirnya reformasi, sejatinya tidak terlalu berkaitan dengan kebutuhan ideologis muslim atas nilai dan tradisi berhukum. Beberapa poin perjuangan reformasi malah lebih banyak mengetengahkan isu-isu modernism dan demokrasi yang berkelindan dengan liberalism dan kapitalisme.
Dalam konteks yang lebih dalam, reformasi yang mengusung tema keterbukaan dan kebebasan, sejatinya telah membuka keran yang begitu lebar bagi infiltrasi nilai-nilai sekularisme dalam kehidupan berbangsa serta tradisi berhukum kita. Problem sistemik dalam tradisi berhukum kita adalah usaha untuk mengalienasi nilai dan ajaran agama dari sistem dan produk hukum negara.
Dalih yang senantiasa digunakan adalah “Indonesia bukan negara agama”, serta adagium “Bhineka Tunggal Ika”. Kedua dalil itu menjadi landasan bagi penolakan perda Syariah, karena dianggap intoleran, mengganggu persatuan dan kesatuan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
Terlepas dari realitas di atas, perkembangan sistem hukum kita pasca reformasi bukannya tidak mengakomodasi ajaran agama. Buktinya, pasca reformasi ini beberapa undang-undang dan regulasi dengan nomenklatur syari’ah dibuat dan beroperasi, semisal akomodasi pengaturan zakat, perbankan dan investasi syari’ah.
Refleksi kritisnya bahwa pengaturan yang dibuat dilandasi atas pertimbangan potensi ekonomi dan permodalan yang bisa didapat dari ummat. Jika dilihat dari aspek kemanfaatannya, maka sejatinya yang mengambil manfaatan terbesar dari undang-undang dan regulasi tersebut adalah negara dan pemodal.
Perubahan substansi Pasal 33 berimplikasi pada maraknya privatisasi dan kapitalisasi sumber daya alam. Terlebih negara negara menghadirkan undang-undang dan regulasi yang memungkinkan privatisasi berkembang baik.
Problem substansial dari lahirnya reformasi sejatinya adalah inkonsistensi negara dalam menjalankan konsitusi, serta degradasi moralitas dan orientasi kebangsaan penyelenggara negara. Apakah permasalahan itu dapat diakhiri melalui langkah amandemen konstitusi? Wallahu a’lam bisshowab.***