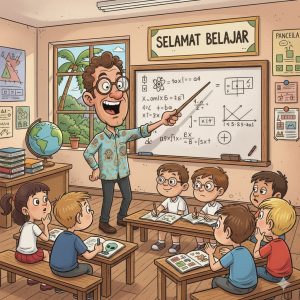MAKLUMAT — Pagi itu, udara di kantor-kantor PCNU di berbagai daerah terasa berbeda. Di banyak grup WhatsApp warga Nahdliyin, pesan demi pesan berloncatan: kabar “pemecatan” Ketua Umum PBNU, keputusan Syuriyah, serta tanggapan para kiai dari berbagai wilayah. Suasana yang biasanya tenang berubah menjadi ruang diskusi yang panas, penuh tanya, penuh kecemasan, sekaligus penuh harapan bahwa konflik ini segera mereda.

Retaknya kepemimpinan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bukan sekadar peristiwa administratif. Bagi jutaan warga NU, ini adalah guncangan emosional. NU bukan hanya organisasi; ia adalah identitas, rumah besar, dan payung tradisi yang menaungi kehidupan sosial-keagamaan masyarakat hingga ke kampung-kampung paling terpencil.
Konflik ini pecah setelah muncul risalah harian Syuriyah PBNU yang meminta Ketua Umum mundur. Risalah itu dibaca luas sebagai sinyal ketidakharmonisan di jajaran pimpinan teratas NU. Sejumlah ulama menyebut adanya masalah tata kelola dan penentuan arah kebijakan. Pihak lain menilai proses pengambilan keputusan itu berlangsung terlalu cepat, tanpa memberi ruang yang cukup untuk tabayyun dan audit internal yang sedang berjalan.
Di titik inilah persoalan bermula. Ketika tata kelola modern bertemu pola komunikasi tradisional yang sarat tata krama, gesekan bisa terjadi. Organisasi sebesar PBNU, dengan sejarah panjang dan basis jutaan anggota, memiliki ritme tersendiri dalam menyelesaikan polemik. Namun kali ini, ritme itu terganggu.
Keputusan Syuriyah untuk mengambil alih wewenang organisasi membuat situasi semakin tegang. Ada yang menyebutnya langkah penyelamatan, ada pula yang menilainya sebagai keputusan yang terlalu drastis. Di ruang-ruang diskusi NU, pertanyaan terus mengemuka. Apakah konflik ini soal kebijakan, soal komunikasi, atau soal ketegangan internal yang sudah lama terpendam?
Tidak perlu waktu lama bagi getaran konflik di tingkat pusat untuk merembet ke daerah. Di Surabaya, seorang pengasuh pesantren mengatakan bahwa santri dan wali murid bertanya-tanya, “Apa benar NU pecah?” Di sebuah desa di Jawa Tengah, para guru madrasah membicarakan perkembangan ini di sela-sela kegiatan belajar mengajar.
Di Gresik, seorang tokoh masyarakat menyampaikan kegelisahannya, “Kalau kiai di pusat tidak rukun, bagaimana dengan kami di bawah? Jamaah butuh keteduhan.”
Kegelisahan itu wajar. Selama ini NU menjadi jangkar moral dan penyejuk di tengah hiruk pikuk politik nasional. Ketika jangkar itu goyah, masyarakat di tingkat bawah ikut merasakan badai.
Namun, di tengah kecemasan itu, ada pula suara-suara bijak. Beberapa PWNU dan PCNU menyerukan penyelesaian damai, kembali pada AD/ART, dan menghormati mekanisme organisasi. Mereka mengingatkan bahwa sejarah NU selalu dipenuhi ujian, dan setiap ujian justru melahirkan kedewasaan baru.
Ruang Sunyi Para Kiai: Tempat NU Menemukan Kejernihan
Dalam tradisi NU, konflik bukan penyebab perpecahan; ia adalah undangan untuk bermusyawarah. Dalam beberapa hari setelah kabar pecah, sejumlah kiai sepuh dikabarkan mengadakan pertemuan tertutup. Mereka tidak ingin kegaduhan berlanjut, tidak ingin jamaah resah, dan tidak ingin NU tercabik oleh kepentingan politik.
Salah satu kisah yang menggugah datang dari seorang kiai sepuh di Jawa Timur. Ketika ditanya bagaimana NU harus bersikap, ia menjawab pelan, “NU itu rumah besar. Jika lantainya retak, jangan dirobohkan rumahnya. Perbaiki retaknya, kuatkan pondasinya.”
Jawaban itu menggambarkan keteduhan yang selama ini menjadi wajah NU. Bahwa di tengah konflik, selalu ada ruang sunyi di mana para kiai berkumpul, menarik napas panjang, dan mencari solusi terbaik untuk jamaah.
Persimpangan Jalan: Membaca Masa Depan NU
Konflik kepemimpinan ini menempatkan NU di persimpangan jalan penting. Ada dua kemungkinan: retakan ini membesar dan menimbulkan polarisasi tajam, atau menjadi titik balik untuk pembenahan menyeluruh.
Sejumlah kalangan mendesak agar NU memperkuat sistem tata kelola, memperjelas mekanisme pengambilan keputusan, serta memastikan komunikasi antara Syuriyah dan Tanfidziyah berjalan proporsional. NU bukan lagi organisasi yang hidup di era analog; banyak keputusan kini mendapat sorotan publik secara real time. Ketidakjelasan sedikit saja dapat memicu spekulasi.
Di sinilah NU perlu adaptif tanpa kehilangan ruhnya: menguatkan struktur modern, tetapi tetap berpegangan pada tradisi musyawarah yang menjadi identitasnya.
Ketika Harapan Selalu Lebih Besar dari Kegelisahan
Terlepas dari seluruh ketegangan, satu hal masih sangat jelas: warga NU mencintai organisasinya. Cinta itulah yang membuat mereka peduli, gelisah, bahkan marah ketika melihat rumah besar mereka terguncang.
Tetapi cinta yang sama pula yang akan mendorong rekonsiliasi. NU terlalu besar untuk diruntuhkan oleh konflik internal. Ia sudah melewati zaman kolonial, revolusi, pergolakan politik, hingga reformasi. Retakan kali ini mungkin yang paling keras dalam beberapa tahun terakhir, tetapi bukan yang paling berat sepanjang sejarahnya.
Pada akhirnya, warga NU menunggu keputusan terbaik dari para pemimpinnya. Mereka berharap, dalam waktu dekat, suasana kembali teduh. Agar pesantren kembali fokus mendidik santri, madrasah kembali tenang mengajar murid, dan masyarakat kembali melihat NU sebagai cahaya penuntun bukan sumber gaduh.
Karena sesungguhnya, NU bukan sekadar organisasi. Ia adalah keluarga besar. Dan keluarga, sekeras apa pun bertengkar, pada akhirnya akan mencari jalan pulang.***