MAKLUMAT – Malam di Desa Ampeldento, Karangploso, Malang, sering kali bukan hanya dihuni suara jangkrik. Dari pematang sawah, pergerakan tikus terdengar samar, merayap menuju batang padi yang baru berbulir.
Pagi harinya, burung-burung datang berkerumun, mencuri bulir yang mulai menguning. Serangan hama semacam ini menjadi momok yang terus menghantui petani padi.
Selama ini, upaya menghalau tikus dan burung mengandalkan cara tradisional: jebakan, orang-orangan sawah, hingga pestisida kimia. Sayangnya, hasilnya sering tak sepadan. Pestisida bahkan menimbulkan masalah baru: tanah dan air ikut tercemar, sementara hama tetap saja kembali.
Pengabdian pada Lingkungan
Berangkat dari keresahan itu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mencoba menawarkan solusi berbeda. Lewat program PPK Ormawa, mereka menghadirkan inovasi pertanian berbasis teknologi bernama Integrasi Smart Farming 5.0 dengan SolarSonic IoT Guard.
Inovasi yang didanai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdiktiristek) ini dirancang untuk membantu petani menjaga sawah. Metode yang digunakan tanpa harus merusak lingkungan.
“Alat ini bekerja otomatis dan, pengendaliannya cukup melalui aplikasi,” jelas Galih Raka Yudistira, Ketua Himpunan Mahasiswa Agribisnis (Himagri) UMM.
Petani tidak lagi bergantung pada cara-cara lama yang tidak efektif. Teknologi ini, mampu menghasilkan panen lebih terjamin dari serangan hama.
SolarSonic IoT Guard memiliki empat komponen utama. Raspberry sebagai mikrokontroler, sedangkan panel surya dan baterai sebagai sumber energi terbarukan.
Adapun kamera thermal berfungsi mendeteksi keberadaan hama, dan terakhir speaker ultrasonik mampu mengusir tikus dan burung dengan gelombang suara khusus.
Implementasi Kepemimpinan
Alat ini beroperasi 24 jam penuh. Malam hari, kamera thermal mendeteksi pergerakan tikus. Jika terdeteksi, speaker langsung memancarkan suara pengusir.
Pagi hingga sore, mode berpindah ke pengusir burung. Semua sistem berjalan otomatis, sementara petani cukup memantau atau menyesuaikan pengaturan lewat aplikasi IoT.
Meski begitu, jalan menuju inovasi ini tidak mulus. Sulit menemukan beberapa komponen di Malang, harga pengadaan relatif tinggi, dan integrasi sistem berbasis IoT butuh waktu belajar panjang.
Namun hasilnya sepadan. Teknologi ini terbukti mampu menekan kerugian akibat serangan hama, meningkatkan hasil panen, sekaligus menjaga lingkungan dari dampak pestisida.
Bagi mahasiswa, pengalaman ini juga berarti lebih dari sekadar proyek akademik. Mereka belajar memimpin, bertanggung jawab, dan berkolaborasi dengan petani desa. Sebuah proses yang menegaskan bahwa ilmu di kampus bisa benar-benar menjawab masalah nyata di lapangan.







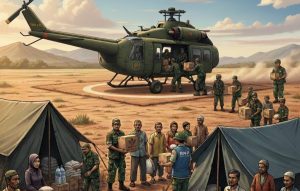
Comments