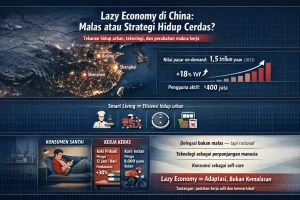Perampasan yang Bersifat Struktural
MAKLUMAT — Di hamparan republik ini, tanah bukan sekadar benda—ia adalah tempat bernapas, narasi sejarah, dan jaringan relasi sosial-ekologis yang menopang hidup. Namun sejak masa kolonial sampai era pembangunan besar-besaran, tanah berubah wujud, dari ruang hidup menjadi aset yang dapat “ditumpangi”, diukur, dan diperdagangkan.
Sebagai konsekuensi, konflik agraria berulang dalam pola yang familiar, masyarakat adat dan petani lokal kehilangan akses atas hutan, ladang, dan sumber mata pencaharian, sementara izin-izin korporasi, kebijakan pembangunan, dan aparat negara sering kali hadir sebagai alat legitimasi perampasan.
Laporan inkuiri lapangan mengumpulkan empat puluh kasus konflik masyarakat hukum adat yang menunjukkan betapa meluas dan sistematis persoalan ini—bahwa sekitar 70 juta orang yang tergolong masyarakat hukum adat (sekitar 20% penduduk) hidup dalam ketidakpastian hak atas wilayahnya, dan sebagian besar bergantung pada kawasan hutan sebagai sumber hidup. Kasus-kasus itu memotret pola penggusuran, kriminalisasi, dan pemiskinan yang berlangsung lama.
Masalah ini bukan sekadar “kesalahan teknis” dalam pemberian izin. Ia adalah resultan kebijakan, sejarah, dan ekonomi warisan “agrarische wet” (kolonial), pembentukan rezim kehutanan yang menyatakan banyak kawasan sebagai “hutan negara”, orientasi pembangunan Orde Baru, serta gelombang liberalisasi pasca-Reformasi yang membuka ruang bagi konsesi besar—semua berkontribusi pada akumulasi lahan oleh aktor-aktor berkuasa.
Dalam konteks Tanah Papua, misalnya, data deforestasi 2001–2020 menunjukkan hilangnya 641,4 ribu hektar hutan alam, dan setidaknya 20% wilayah daratan telah dibebani izin-konsesi industri ekstraktif (sawit, tambang, HPH, HTI). Ini bukan sekadar statistik, ini adalah gambaran suatu proses perampasan yang bersifat struktural.
Ekologi Politik Ketidakadilan Agraria
Ekologi politik menegaskan sebuah premis sederhana tapi mengganggu, degradasi lingkungan dan konflik agraria bukan masalah teknis—mereka adalah produk relasi kuasa. Pemikir-pemikir seperti Piers Blaikie dan Harold Brookfield (Land Degradation and Society, 1987), Michael Watts (Silent Violence, 1983), Arturo Escobar (Encountering Development, 1995), dan Paul Robbins (Political Ecology: A Critical Introduction, 2012) menegaskan bahwa perubahan lingkungan selalu terkait dengan konteks politik, ekonomi, dan ideologi. Perspektif ini memaksa kita membaca siapa yang membuat keputusan, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan ketika hutan ditebang atau ladang diubah menjadi perkebunan skala luas.
Pembacaan empirisnya cerah sekaligus menyayat. Di banyak kasus, masyarakat adat yang hidup berabad-abad di wilayah tertentu mendapati lahan “milik negara” tiba-tiba diberi konsesi kepada perusahaan, dan ketika mereka menolak—jawaban negara adalah aparat keamanan. Narasi untuk “pembangunan nasional” atau “ketahanan pangan” digunakan untuk menjustifikasi pembukaan lahan jutaan hektar, sementara mekanisme konsultasi yang sejatinya harus menjamin partisipasi—seperti prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent)—sering kali diabaikan atau dipreteli maknanya. Hasilnya, kriminalisasi aktivis, rusaknya sumber air dan makanan lokal, serta hilangnya pengetahuan tradisional yang terkait dengan pengelolaan ekosistem. Bukti lapangan menunjukkan bagaimana perempuan, penjaga ekonomi rumah tangga di banyak komunitas adat, menjadi korban utama karena rusaknya ladang dan hutan sumber penghidupan.
Dalam ekologi politik, konflik agraria adalah konflik distribusi beban ekologis dan akses terhadap manfaat. Data tentang hilangnya 641,4 ribu ha hutan di Papua (2001–2020) bukan hanya ukuran kerusakan alam, melainkan juga penanda kegagalan sistem politik-ekonomi yang membiarkan akses hutan dikuasai aktor eksternal tanpa kompensasi sosial-ekologis yang adil. Statistik konsesi—1,8 juta ha untuk sawit, 436,5 ribu ha izin pertambangan, HPH 5,5 juta ha—mengilustrasikan bagaimana relasi kekuasaan menyusun peta ruang, ruang hidup masyarakat dilipat-lipatkan demi mesin produksi global.
Ekologi politik juga mengingatkan kita pada dimensi kultural—tanah sebagai tempat berkuburnya cerita, ritual, dan pengetahuan. Ketika hutan kemenyan di Pandumaan–Sipituhuta ditebang, yang hilang bukan hanya pohon, tetapi juga jalinan simbolik dan mata pencaharian komunitas—dampak yang secara sosial dan psikologis mendalam dan diwariskan antar generasi. Kasus-kasus ini menceritakan bahwa penyelesaian harus melibatkan pemulihan hak, rekonstruksi pengetahuan lokal, dan pembaruan ruang publik demokratis yang memungkinkan deliberasi otentik.
Ketidakadilan Agraria dan Akumulasi Kapitalisme
David Harvey memperkenalkan konsep “accumulation by dispossession”—versi kontemporer dari akumulasi primitif—untuk menjelaskan bagaimana kapitalisme modern terus berkembang melalui perampasan aset sosial, tanah, hak kolektif, dan layanan ekosistem (The New Imperialism, 2003). Di Indonesia, mekanisme ini terwujud lewat pemberian konsesi, deregulasi lahan, dan skema “penyediaan lahan untuk investasi” yang secara de facto memfasilitasi akumulasi modal oleh segelintir aktor—perusahaan besar, oligarki lokal, bahkan korporasi transnasional.
Perspektif Harvey menjelaskan kenapa konflik agraria bukan sekadar “kesalahan administratif”, ia adalah bagian dari strategi kapital untuk merekayasa ruang agar sesuai dengan kebutuhan akumulasi. Praktik “market-led land reform” (sertifikasi, bank tanah, HGU besar) sering kali menukar janji kepastian hukum bagi petani dengan penciptaan pasar lahan yang justru memudahkan akumulasi. Beberapa kajian historis menegaskan transformasi kebijakan agraria yang, alih-alih menyelesaikan ketimpangan kepemilikan, menyediakan kesempatan bagi pemodal untuk menguasai lahan dalam skala masif.
Data empiris mendukung tesis ini, praktik pemberian izin luas, konsentrasi lahan pada korporasi besar, dan “reproduksi” oligarki agraria menimbulkan apa yang disebut sebagai kutukan sumber daya—kekayaan SDA yang tidak diterjemahkan menjadi kesejahteraan lokal. Contoh Kaltim yang sering dikutip, 89% lahan dikuasai oleh perusahaan, sementara hanya 4% dikuasai masyarakat lokal; pendapatan besar mengalir keluar daerah sehingga hanya sebagian kecil manfaat tersisa untuk masyarakat setempat—pelajaran yang ditakuti banyak pengamat ketika melihat rencana skala besar di Papua.
Dari sudut pandang Harvey, penghormatan terhadap hak adat bukan sekadar moral imperative, tapi juga hambatan terhadap mekanisme dispossession yang menggerakkan akumulasi modal. Dengan kata lain, melindungi hak-hak komunitas lokal dan memperkuat pengelolaan kolektif adalah salah satu cara paling efektif untuk menantang logika akumulasi ekstraktif—karena ia memutus jalur perampasan yang menjadi bahan bakar pertumbuhan modal jangka pendek.
Meraba Jalan Keluar
Membaca masalah lewat kedua lensa tadi memberi arah kebijakan dan praktik, solusi teknis tanpa keinginan kuat merombak relasi kuasa hanya akan mempertajam ketidakadilan, retorika partisipasi tanpa redistribusi kewenangan adalah omomg kosong belaka. Berikut beberapa tawaran praktis yang konkret dan politis —bukan sekadar wishful thinking.
Pertama, pengakuan penuh dan implementasi hak masyarakat hukum adat; pengakuan wilayah adat bukan hanya akta di atas kertas; ia mesti disertai pemulihan hak-hak pengelolaan, pembatalan konsesi yang menyalahi FPIC, dan mekanisme restoratif untuk korban kriminalisasi. Putusan MK yang mengakui hutan adat harus dipercepat pelaksanaannya melalui peta partisipatif yang dilindungi hukum. Data lapangan menunjukkan kebutuhan ini mendesak di puluhan kasus.
Kedua, moratorium penerbitan izin baru dan review komprehensif terhadap izin lama, terutama di daerah-daerah kritis—seperti banyak wilayah Papua—perlu moratorium sementara sambil dilakukan audit independen atas semua izin berdasarkan kriteria FPIC, dampak lingkungan, dan tata ruang lokal. Greenpeace merekomendasikan pencabutan izin yang tidak memenuhi prinsip-prinsip ini.
Ketiga, desain ulang politik agraria, dari komodifikasi ke fungsi sosial-ekologis; mengembalikan esensi UUPA 1960—tanah sebagai instrumen kesejahteraan—melalui kebijakan yang mengutamakan redistribusi substantif, dukungan teknis bagi pengelolaan lokal, dan skema ekonomi yang menghargai jasa ekosistem. Ini berarti menolak model “growth at any cost” dan menggantinya dengan ukuran kesejahteraan yang lebih holistik.
Keempat, penguatan kapasitas hukum dan politik masyarakat adat, apat berupa bantuan hukum, peta partisipatif, dan sumber daya advokasi harus menjadi prioritas. Kasus-kasus lokal menggarisbawahi bahwa proses litigasi dan negosiasi sering timpang karena ketidaksetaraan kapasitas. Dukungan sistemik dapat memperkecil celah itu.
Kelima, mekanisme akuntabilitas terhadap keterlibatan aparat; penggunaan aparat keamanan dalam menyokong kegiatan korporasi harus diselidiki dan dihentikan. Ada banyak dokumentasi tentang kriminalisasi warga yang menentang perampasan lahan—ini menuntut reformasi prosedural dan sanksi tegas jika aparat melanggar HAM.
Keenam, model pembangunan berbasis kedaulatan lokal; bangun ekonomi lokal yang berbasis kearifan ekologis (sagu, rotan, pertanian agroforestry) dengan dukungan pasar adil dan insentif kebijakan—sehingga wilayah adat mampu bertahan tanpa tergulung oleh mesin ekstraktif.
Ketidakadilan agraria di Indonesia adalah wajah ganda sejarah: ia adalah warisan kolonial yang bertransformasi menjadi modal-isme kontemporer. Ekologi politik berpandangan bahwa setiap pohon yang ditebang sekaligus memusnahkan pengetahuan dan relasi sosial; perspektif akumulasi oleh kapitalisme mengungkapkan bagaimana perampasan itu menjadi mesin akumulasi modal. Menyusun solusi bukan hanya soal memperbaiki regulasi—itu soal meredefinisi siapa yang berhak menentukan masa depan ruang hidup di negeri ini.
Politik yang dikerjakan menuntut keberpihakan—bukan sekadar retorika—kepada komunitas yang selama ini menanggung beban. Ini politik yang membangun alat, kapasitas, dan ruang deliberasi agar hak atas tanah bukan lagi barang yang dilelang di meja birokrat, melainkan fondasi kehidupan kolektif. Kita bisa memilih, melanjutkan perampasan dengan kertas izin, atau memulai rekonstruksi yang menempatkan manusia dan ekologi di pusat perhitungan. Pilihan itu bukan hanya etis, namun ia menentukan apakah republik ini akan menjadi tempat bagi semua atau hanya bagi yang punya modal.
____________
*) Artikel ini sudah pernah dipublikasikan di laman resmi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah dengan judul “Tanah yang Dirampas, Hutan yang Berdarah.”