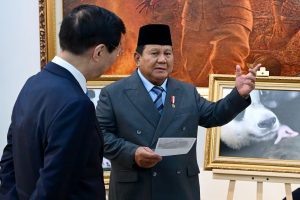MAKLUMAT — Ketua DPP PKS Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Dr Agus Ismail, menyoroti semakin maraknya permasalahan lingkungan hidup yang muncul pasca-pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Ia menyebut, memang sempat terjadi tren penurunan deforestasi, namun itu tidak bertahan lama. Lonjakan kerusakan hutan pada periode 2023–2024, pemutihan 1,7 juta hektare sawit ilegal, serta melemahnya perlindungan kawasan konservasi menunjukkan bahwa regulasi tersebut membawa konsekuensi serius bagi masa depan hutan Indonesia.
Menurut Ismail, UU Cipta Kerja memang dipromosikan sebagai terobosan deregulasi untuk mempercepat investasi dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Namun, dampak pada sektor kehutanan menurutnya tidak main-main. Sederet perubahan yang dibawa UU Cipta Kerja mulai dari perizinan, tata ruang, hingga penegakan hukum melahirkan jejak ekologis yang kini semakin tampak.
“Empat tahun setelah berjalan, kita melihat bahwa prinsip kehati-hatian dalam perizinan melemah, kapasitas pengawasan tidak mengimbangi percepatan investasi, dan penegakan hukum belum cukup memberikan efek jera. Tanpa koreksi, fluktuasi deforestasi akan terus terjadi dan menggerus kekayaan hayati Indonesia,” sorotnya.
Angka Deforestasi yang Kembali Meningkat
Berdasarkan data KLHK yang dirangkum Forest Watch Indonesia, sebelum UU Cipta Kerja diterbitkan, tingkat deforestasi Indonesia berada di kisaran 620 ribu hektare per tahun pada periode 2015–2019. Setelah regulasi tersebut berlaku, angka itu turun menjadi sekitar 100 ribu hektare per tahun pada 2020–2022. Kala itu, pemerintah menyebutnya sebagai bukti keberhasilan kebijakan.
Kendati demikian, laporan terbaru Auriga Nusantara menunjukkan tren sebaliknya. Angka deforestasi kembali meningkat menjadi 257 ribu hektare pada tahun 2023 dan naik lagi menjadi 261 ribu hektare pada tahun 2024.
Menurut Ismail, data itu menunjukkan bahwa penurunan deforestasi pasca-2020 bukan hasil perubahan struktural dalam kebijakan, melainkan dampak eksternal seperti pandemi, melemahnya pasar global, hingga berkurangnya aktivitas industri kala itu.
Kawasan Konservasi Mulai Terancam
Lebih jauh, Ismail mengungkapkan bahwa peningkatan deforestasi kini bahkan merambah ke kawasan-kawasan konservasi. Pada tahun 2024, sekitar 7.700 hektare hutan hilang di kawasan konservasi, dan lebih dari 6.000 hektare di antaranya terjadi di taman nasional.
Ia mencontohkan pada kasus di Taman Nasional Tesso Nilo di Riau, yang kehilangan 251 hektare dalam satu tahun. Menurutnya, kerusakan yang terjadi di kawasan konservasi yang seharusnya memiliki tingkat perlindungan tinggi menunjukkan lemahnya struktur.
“Kerusakan di kawasan dengan tingkat perlindungan tertinggi menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya ekspansi, tetapi juga melemahnya perlindungan struktural,” tandasnya.
Pemutihan Sawit Ilegal: Risiko Baru
Tak cuma itu, Ismail juga menyoroti kebijakan pemutihan sekitar 1,7 juta hektare kebun sawit ilegalm yang dilandaskan pada Pasal 110A-110B UU Cipta Kerja.
Menurutnya, kebijakan tersebut membawa setidaknya empat risiko utama. Pertama, melemahnya efek jera karena pelaku perambahan terhindar dari konsekuensi hukum.
Kedua, Munculnya moral hazard, yakni peluang pelanggaran baru menunggu legalisasi berikutnya. Ketiga, Dorongan ekspansi ke wilayah frontier, termasuk koridor penyangga taman nasional dan suaka margasatwa. Keempat, Penyelesaian konflik tenurial yang tidak substantif, sementara masyarakat lokal justru ditekan untuk beradaptasi.
Perubahan orientasi kebijakan nasional, lanjut Ismail, juga turut mempengaruhi situasi tersebut. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata dia, moratorium sawit dan pengetatan izin tambang menahan laju deforestasi.
“Namun era berikutnya mengedepankan hilirisasi dan ekspansi agribisnis, sehingga diperlukan alat regulasi yang lebih ketat. Sayangnya, UU CK justru mempermudah perizinan sekaligus memperlemah pengawasan,” terangnya.
Tak Cukup Revisi Regulasi, Harus Koreksi Paradigma
Lebih lanjut, Ismail menegaskan bahwa solusi persoalan deforestasi tidak cukup dengan revisi teknis regulasi, melainkan harus melakukan perubahan paradigma.
“Yang diperlukan bukan sekadar revisi pasal, tetapi koreksi paradigma,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus menempatkan perlindungan ekosistem sebagai landasan utama pembangunan, bukan malah menjadi tantangan ataupun hambatan.
“Tanpa itu, kita menghadapi risiko ekonomi jangka panjang, mulai dari hilangnya jasa ekosistem hingga terganggunya komitmen penurunan emisi,” pungkas Ismail.