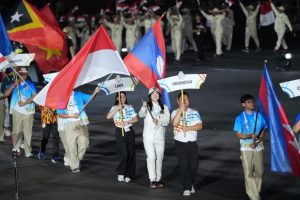KETUA Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir menegaskan, dalam konteks politik, Muhammadiyah berpandangan bahwa segala hal terkaitnya adalah sebagai ranah ijtihad. Hal itu diperkuat oleh fakta sejarah bahwa tidak ada sebuah sistem politik Islam yang definitif, absolut, dan tunggal.
Menurut dia, Nabi Muhammad tidak pernah secara ‘jahr’ (secara terang, jelas, gamblang) menyebutkan seperti apa bentuk negara atau sistem politik yang paling tepat, bahkan hingga menyebabkan perdebatan panjang di kalangan para sahabat dan umat Islam, sepeninggal Rasulullah.
“Realitas ini sebagai sinyal kuat bagi kita, baik pembelajar ilmu politik Islam maupun kita sebagai elit maupun umat Islam untuk menempatkan politik yang rentangan aspek dan cara pandangnya yang A sampai Z,” terang Prof Haedar, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (29/9/2023) lalu.
Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu menjelaskan, umat Islam modern tidak memiliki pilihan tunggal tentang sistem politik, baik sebgai entitas nation maupun sebagai entitas state di negara-negara Islam. Hal itu disebabkan realitas bahwa Nabi Muhammadiyah tidak pernah menetapkan atau menunjukkan sistem politik tunggal, baik dalam Al-Quran maupun hadits.
“Karena memang bahan dasarnya berada pada wilayah ijtihad. Masalah kemudian terjadi di kemudian hari ada golongan-golongan yang dengan pandangan absolute, dan memutlakkan pandangan-pandangan politik dan sistem politik tunggal,” ungkap Prof Haedar.
Lebih lanjut, menyitir pandangan dari Bahtiar Effendy, Prof Haedar menerangkan, sistem politik Islam kehilangan tiga aspek, disebabkan oleh semakin menguatnya kelompok-kelompok islamis yang kemudian berpandangan tunggal dan absolut terhadap sistem politik.
Pertama, kata dia, umat Islam telah kehilangan kemampuan dalam negosiasi, baik di kalangan sendiri maupun dengan pihak lain. “Kedua, karena sistem politik tunggal dan serba prinsip umat Islam kehilangan kemampuan untuk beradaptasi. Ketiga, karena sistem politik tunggal tersebut umat Islam kehilangan kemampuan untuk berkompromi,” tandas Prof Haedar.
Dampak dari kegagalan dalam mengelola tiga aspek tersebut, menurut Prof Haedar menyebabkan kegagalan politik Islam, yang kemudian itu semakin menambah dan mengakumulasi politik Islam menjadi semakin rigid, reaktif, semakin tunggal, dan kegagalannya semakin menguat. “Dari ini kemudian lahirlah neo-revivalisme Islam dan neo-fundamentalisme Islam,” kata dia.
Ketika melihat kecenderungan sikap partai politik yang mengatasnamakan Islam saat ini, Prof Haedar berpendapat, bahwa mereka lebih cenderung sebagai kelompok neo-fundamentalisme Islam. Bagi dia, kecenderungan tersebut memiliki potensi besar kegagalan-kegagalan yang akan terus berulang. (*)
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto