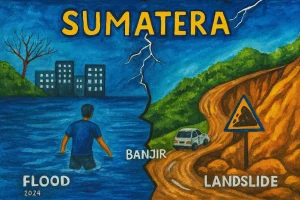MAKLUMAT — Pasca kerusuhan 28-31 agustus 2025 dan kemarahan, kekecewaan yang masih terpendam, serta tuntutan mahasiswa 17+8 yang kemarin juga diobrolkan oleh Pesiden Prabowo dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) beranggotakan beberapa tokoh bangsa lintas agama, yang dipimpin Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, bisa dirasakan secara kuat bahwa ini bukan hanya soal tuntutan tetapi ajakan kontemplasi sistem kekuasaan, untuk setiap warga bangsa yang masih peduli dengan masa depan negara-bangsa Indonesia.
Kontemplasinya mungkin bisa dilakukan dengan memaknai berbagai kisah penderitaan rakyat dan kisah perjuangan hidup rakyat kecil. Salah satunya cerita dari Afrika Timur.

Mengapa diambil cerita dari Afrika Timur? Ada 4 alasan penulis: (a) Untuk memberikan nuansa universalitas dan allegori (teknik sastra untuk mengungkap simbol-metafora lebih dalam), (b) Anonimitas yang menghidandarkan dari bias politik, kultural dan identitas, (c) Cermin yang lebih jernih lepas dari prasangka personal, (d) Membangun solidaritas global.
Kisah ini dicuplik dari pesan WA yang beredar (entah siapa penulis yang hebat ini). Alkisah, pada tahun 1985, di sebuah desa yang tenang di Afrika Timur, seorang pria bernama Daniel berdiri tanpa alas kaki bersama ketiga putrinya. Istrinya meninggal saat melahirkan setahun sebelumnya. Ia tidak pernah menikah lagi. Ia tidak punya waktu. Ia adalah seorang petani, tukang bangunan, ayah, dan seorang pemimpi sekaligus.
Rumah mereka tidak memiliki listrik. Terkadang, makan malam mereka hanya berupa akar-akaran rebus dan air. Namun yang mereka miliki, yang Daniel pastikan selalu mereka miliki, adalah harga diri.
Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia membangunkan anak-anak perempuannya dan mengajak mereka berjalan kaki sejauh tiga kilometer ke sekolah. Ia sendiri tidak bisa membaca atau menulis, tetapi ia duduk di luar kelas setiap hari, menunggu di tempat teduh, agar mereka tidak perlu berjalan pulang sendirian. Terkadang ia tidak makan agar mereka bisa membeli pensil. Ia menjual cincin kawinnya untuk membayar biaya ujian. Ia bekerja tiga pekerjaan selama musim panen hanya untuk membeli buku pelajaran bekas banyak halamannya hilang.
Orang-orang tertawa: “Mereka kan anak perempuan,” kata mereka. “Masa depan apa yang mereka miliki?” Daniel tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan di samping mereka.
Tahun-tahun berlalu. Satu per satu, mereka lulus. Satu per satu, mereka mendapatkan beasiswa. Dan satu per satu… mereka menyeberangi samudra.
Pada tahun 2025, 40 tahun setelah foto itu diambil, dunia melihat sesuatu yang tak terduga: “Sebuah citra baru dari pria yang sama, berdiri dengan gagah, kali ini di depan sebuah rumah sakit, bersama ketiga putrinya, semuanya mengenakan jas putih. Para dokter. Semuanya!”
Ketika ditanya bagaimana perasaannya, Daniel menangis pelan dan berbisik, “Aku tak pernah memberi mereka dunia. Aku tak pernah membiarkan dunia merenggut harapan mereka.” Ia bercocok tanam dengan tangannya, tetapi ia membesarkan para dokter dengan hatinya.
Dan dalam bayang-bayang tenang seorang pria yang tak pernah dikenal dunia, tiga gadis bangkit… dan mengubahnya.
Kisah Daniel dari Afrika Timur ini, meskipun berlatar belakang sederhana dan personal, adalah sebuah allegori yang sangat kuat untuk mengkritik sistem kekuasaan oligarkis dan dominasi paham neoliberal di Indonesia. Dengan menggunakan lensa teori sosial dan filosofis, kita dapat belajar mengulasnya secara literatif.
Kisah Daniel dari Afrika Timur, mungkin juga banyak kisah di negeri sendiri, di kalangan masyarakat bawah, memang sangat efektif digunakan sebagai kritik kontemplatif, sebuah kritik yang tidak hanya menuntut perubahan kebijakan, tetapi juga mengajak kita untuk merenungkan ulang nilai-nilai dasar, prioritas, sistem politik kekuasaan dan struktur masyarakat kita.
Kekuatan Soft Power
Kisah Ini menunjukkan kekuatan ‘Soft Power’ yang diabaikan sistem. Sistem kekuasaan oligarkis dan neoliberal sering kali hanya mengakui dan menghargai satu jenis kekuatan: ‘kekuatan ekonomi dan politik’ (uang, koneksi, kewenangan). Kisah di atas memperlihatkan 3 kekuatan alternatif yang justru lebih fundamental yaitu kekuatan moral: harga diri, integritas, dan pengorbanan. Kekuatan sosial: yaitu ikatan keluarga, dukungan tanpa syarat, dan ketekunan. Kekuatan kultura, yaitu keyakinan akan nilai pendidikan, meski ia sendiri buta huruf.
Kisah ini memaksa kita untuk bertanya, “Apakah kita, sebagai masyarakat atau bangsa, hanya mengukur kesuksesan berdasarkan GDP dan kekayaan material? Sudahkah kita mengabaikan dan tidak memelihara jenis ‘modal’ yang justru merupakan fondasi sesungguhnya dari peradaban yang besar, yaitu karakter dan keluarga?”
Logika Investasi Sempit
Kisah di atas juga membalikkan logika “investasi” yang sempit. Logika neoliberal mendefinisikan investasi secara sempit sebagai penanaman modal untuk keuntungan finansial. Kisah kita di atas melakukan investasi yang sama sekali berbeda, yaitu investasi pada manusia dan investasi jangka panjang yang tekun.
Apakah sistem ekonomi dan politik kita dirancang untuk mendukung jenis investasi jangka panjang dan berbasis manusia seperti ini? Ataukah kita hanya mengejar pertumbuhan ekonomi kuartalan yang justru mungkin menggerogoti fondasi manusiawi kita?
Absurditas Prasangka
Kisah diatas menelanjangi absurditas prasangka dan diskriminasi. Kalimat ‘Mereka kan anak perempuan,’ dan ‘Masa depan apa yang mereka miliki?’ adalah inti dari kritik kontemplatif terhadap hegemoni budaya. Daniel tidak berdebat dengan orang-orang itu. Ia membungkam mereka dengan tindakan. Kesuksesan anak-anaknya membuktikan bahwa prasangka tersebut salah dan picik.
Berapa banyak potensi bangsa yang kita sia-siakan karena prasangka semacam ini? Baik karena prasangka gender, ekonomi, suku, maupun agama. Kisah Daniel mengajak kita untuk merenung: apakah kita termasuk dalam ‘orang-orang yang tertawa’ itu, secara langsung atau tidak langsung, dengan membatasi mimpi anak-anak kita sendiri atau orang lain berdasarkan kondisi mereka saat ini?
Definisi ‘Kekayaan’ Alternatif
Kisah Daniel adalah orang yang secara material sangat miskin, tetapi secara nilai-nilai, ia adalah orang paling kaya. Ia kaya akan visi (ia bisa melihat masa depan yang tidak bisa dilihat orang lain), cinta (pengorbanannya adalah wujud cinta yang paling nyata), warisan (warisannya bukan properti atau uang, tetapi transformasi nasib seluruh keluarganya untuk selamanya).
Dalam pusaran konsumerisme dan kapitalisme yang masif, apakah kita sudah mempertanyakan ulang apa arti ‘kaya’ yang sesungguhnya? Apakah kekayaan kita diukur oleh apa yang kita miliki, atau oleh apa yang kita berikan dan wariskan untuk generasi berikut?
Alegori untuk Peran Negara yang Seharusnya
Kisah Daniel, dalam skala mikro, menjalankan fungsi ‘negara kesejahteraan’ yang ideal untuk keluarganya. Ia memberi rasa aman dengan mmenemani anak-anaknya berjalan, melindungi mereka. Ia menyediakan akses dengan bekerja mati-matian menyediakan akses ke pendidikan (buku, pensil, biaya ujian). Ia berkorban untuk kebaikan bersama, dengan tidak makan untuk memastikan anak-anaknya bisa belajar.
Jika seorang ayah miskin dan buta huruf saja bisa melakukan semua ini untuk tiga orang anaknya, apa alasan sebuah negara yang kaya akan sumber daya seperti Indonesia untuk tidak bisa menjalankan fungsi yang sama bagi 270 juta anak bangsa? Di manakah letak kegagalan kita?
Antitesis Logika Sistem Kekuasaan Oligarkis
Kisah Daniel adalah antitesis langsung dari logika oligarkis: Pertama, tentang modal sosial vs modal ekonomi. Oligarki beroperasi dengan logika ‘modal ekonomi menghasilkan lebih banyak modal ekonomi’ yang kemudian diubah menjadi kekuasaan politik. Daniel tidak memiliki modal ekonomi sama sekali. Yang ia miliki adalah modal sosial dan kultural dalam bentuk harga diri, ketekunan, dan cinta.
Investasinya bukan pada saham atau properti, tetapi pada human capital anak-anaknya. Ia membuktikan bahwa bahkan tanpa koneksi, uang, atau privilege, mobilitas sosial vertikal yang dramatis masih mungkin dilakukan melalui pendidikan dan ketabahan. Ini menyiratkan kritik bahwa sistem oligarkis sengaja mengabaikan atau meminggirkan potensi manusia yang begitu besar di Indonesia dengan membiarkan akses pendidikan berkualitas hanya untuk mereka yang mampu.
Kedua, tentang privatisasi vs pengorbanan publik. Oligarki seringkali memprivatisasi keuntungan dan mensosialisasikan kerugian. Daniel melakukan sebaliknya: ia secara personal mengambil semua pengorbanan (tidak makan, menjual cincin, bekerja tiga jobs) untuk mensosialisasikan keuntungan. Keberhasilan anak-anaknya bukan hanya untuk keluarga mereka, tetapi untuk masyarakat luas (menjadi dokter). Sistem oligarkis, sebaliknya, seringkali dilihat mengambil dari publik (SDA, anggaran negara) untuk keuntungan privat.
Ketiga, tentang mentertawakan yang lemah: Kalimat “Mereka kan anak perempuan,” kata mereka. “Masa depan apa yang mereka miliki?” adalah personifikasi dari mindset patriarki dan elitisme yang sering menyertai kekuasaan oligarkis. Ini adalah suara yang merendahkan, membatasi, dan menganggap kelompok tertentu (perempuan, kaum miskin) tidak memiliki masa depan. Perlawanan diam-diam Daniel (“ia hanya terus berjalan di samping mereka”) adalah bentuk resistensi terhadap hegemoni budaya yang diciptakan oleh kekuasaan yang dominan.
Kritik terhadap Hegemoni Neoliberal dan Perlawanan Nilai Pancasila
Neoliberalisme, sebagaimana dikonseptualisasi kan oleh pemikir seperti Milton Friedman dan didorong oleh institusi seperti IMF dan Bank Dunia, percaya pada pasar bebas, minimalisasi peran negara, dan pemaknaan individu sebagai konsumen dan unit ekonomi yang bersaing. Dalam logika ini, pendidikan adalah komoditas, bukan hak publik.
Kisah Daniel menunjukkan betapa kejinya logika neoliberal jika diterapkan secara brutal:
- Pendidikan sebagai Komoditas vs Pendidikan sebagai Hak. Daniel harus menjual cincin kawin dan bekerja tiga jobs hanya untuk membeli buku bekas yang tidak lengkap. Ini adalah gambaran suram dari sistem di mana pendidikan menjadi barang mewah yang harus dibeli. Sistem ini gagal total memenuhi kewajibannya. Daniel terpaksa masuk ke dalam “pasar” pendidikan ini dengan kondisi yang sangat lemah dan tidak setara. Keberhasilannya adalah sebuah kecaman terhadap sistem yang membiarkan warganya berjuang sendiri sedemikian rupa.
- Peran Negara yang Absen vs Kolektivisme Keluarga. Dalam kisah ini, negara sama sekali tidak hadir. Tidak ada sekolah gratis berkualitas, tidak ada bantuan buku, tidak ada jaring pengaman sosial. Yang ada hanyalah Daniel yang berfungsi sebagai ‘negara kesejahteraan miniatur’ untuk ketiga anaknya. Ia menjalankan prinsip kekeluargaan dan gotong royong (sosialisme alami) sekaligus kerja keras dan orientasi pada masa depan (liberal). Inilah esensi dari ideologi Pancasila yang seharusnya: kombinasi berimbang antara semangat kolektivisme dan penghargaan pada individual effort.
- Neoliberal vs Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Logika neoliberal murni akan memandang Daniel dan anak-anaknya sebagai beban statistik yang tidak produktif. Namun, Daniel membuktikan bahwa nilai kemanusiaan (harga diri, cinta, pengorbanan) justru adalah modal yang paling produktif dalam jangka panjang. Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila yang menempatkan manusia dalam konteksnya yang beradab, bukan hanya sebagai angka dalam persaingan pasar.
Catatan Penutup
Pancasila sesungguhnya merupakan Jalan Tengah yang sering terlupakan.
Kisah Daniel adalah metafora yang sempurna untuk Indonesia. Di satu sisi, terdapat tekanan neoliberal yang ingin mempertahankan pendidikan sebagai komoditas eksklusif, sesuatu yang menguntungkan secara ekonomi bagi pemilik modal (oligarki). Di sisi lain, terdapat realitas sosial di mana jutaan Daniel potensial ada, tetapi tidak memiliki sumber daya bahkan untuk membeli “buku yang banyak halamannya hilang”.
Pancasila seharusnya menjadi jalan tengahnya. Bukan sosialisme yang menafikan individualitas, bukan pula liberalisme yang menafikan kolektivitas. Seperti Daniel, negara ideal yang berdasar Pancasila yang seharusnya.
Daniel adalah representasi dari rakyat kecil yang dipinggirkan oleh sistem kekuasaan oligarkis dan logika neoliberal, tetapi pada saat yang sama merupakan penjaga sejati nilai-nilai Pancasila yang substantif: kerja keras, gotong royong, dan kepercayaan pada pendidikan sebagai pilar menuju keadilan. Kisahnya adalah seruan untuk membangun Negara Kesejahteraan (Welfare State) ala Indonesia yang diidealkan oleh para pendiri bangsa, di mana negara hadir secara adil dan membuka jalan bagi setiap warga untuk meraih mimpinya, bukan justru menghalanginya.
Semoga kontemplasi ini didengar Presiden, Parlemen, para penguasa negeri, mahasiswa, para aktivis sejati, para tokoh agama dan masyarakat, para orang tua. Akan makin menarik jika para oligarki (swasta maupun yang birokrat), sejenak rehat dari semangat cari dan menumpuk uang, lalu ikut kontemplasi.