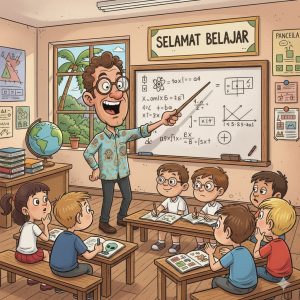MAKLUMAT — Lanskap politik Indonesia hari ini tidak hanya dipenuhi oleh adu gagasan, tetapi juga adu pencitraan. Di tengah ruang publik yang semakin dikendalikan oleh algoritma dan visual, kehadiran Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, membawa warna baru dalam strategi komunikasi politik. Sebagai salah satu aktor politik yang lihai memainkan narasi di era digital. KDM bukan sekadar politisi, ia adalah komunikator publik yang andal, figur digital, konten kreator yang memahami bagaimana membentuk citra diri dan piawai membangun simpati.
Kehadirannya di beberapa media sosial, seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, bukan hanya sebagai media komunikasi, tetapi sebagai arena pertunjukan citra. Dalam kanal-kanal digital tersebut kita bisa menyaksikan bagaimana KDM menyapa warga miskin, membantu pengemis jalanan, berdiskusi dengan mahasiswa, dan yang terbaru menangis saat pulangkan pelajar dari barak militer. Setiap momen direkam, disunting, dan dibingkai dalam narasi humanis yang menyentuh sisi emosional publik.
Tentu fenomena tersebut bukan sesuatu yang keliru. Di era digital, keterhubungan dengan rakyat lewat media sosial menjadi cara baru untuk menjembatani jarak antara pemimpin dan publik. Namun, jika dikaji lebih jernih dengan pendekatan dramaturgi dari Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life (1959), maka gaya komunikasi politik KDM yang kerap tampil di depan kamera perlu menjadi perhatian lebih mendalam.
Sosiolog asal Kanada tersebut menggambarkan kehidupan sosial ibarat panggung teater, di mana setiap individu memainkan peran yang ingin ditampilkan kepada audiens. Dalam konteks ini, video KDM yang tampil membela rakyat kecil, hadir di tengah masyarakat, dan menggaungkan narasi keadilan sosial merupakan panggung depan (front stage).
Namun di balik itu, selalu ada panggung belakang (back stage), tempat strategi komunikasi, kalkulasi politik, dan motif elektoral disusun. Inilah ruang yang tidak terlihat oleh publik, namun sangat menentukan bagaimana KDM merancang penampilannya.
Maka, pertanyaan kritis yang muncul adalah sejauh mana kedekatan yang ditampilkan itu tulus? Dan sejauh mana ia menjadi bagian dari skenario politik yang dirancang untuk kepentingan membangun simpati elektoral?
Bahaya Populisme
Burhanuddin Muhtadi di dalam Populisme, Politik Identitas, dan Dinamika Elektoral (2020) menyebut bahwa dalam populisme elektoral, wacana kedekatan dengan rakyat lebih merupakan strategi politik daripada komitmen ideologis, maka ketika seorang politisi tampil dekat dengan rakyat di ruang digital, agaknya penting untuk mengevaluasi lebih dalam; apakah kebijakan itu berkelanjutan, atau hanya performatif secara elektoral?
Di sinilah titik krusialnya. Era politik digital telah melahirkan banyak ‘tokoh viral‘, tapi belum tentu ‘tokoh transformatif’. Kita membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin yang pandai membuat konten menyentuh hati, kita membutuhkan pemimpin yang mampu mengubah sistem, memperbaiki layanan publik, membangun keadilan sosial, serta menghadirkan kebijakan yang berkelanjutan dan berdampak luas.
KDM dengan segala kreativitas komunikasinya, tentu punya modal sosial yang besar. Namun sebaiknya publik tidak boleh berhenti pada kekaguman visual dan kedekatan simbolik saja. Publik harus menyadari bahwa hari ini dibutuhkan figur yang tidak hanya kuat dalam narasi, tetapi terdepan dalam konsistensi. Konsistensi di sini berarti, apa yang ditampilkan di depan kamera harus sejalan dengan keputusan politik di balik meja birokrasi.
Apakah kebijakannya berpihak pada rakyat miskin? Apakah anggaran disusun untuk memperkuat petani dan nelayan? Apakah ia berani menertibkan mafia tanah dan menindak pelaku perusakan lingkungan? Semua itu bukan diukur dari jumlah like atau komentar di media sosial, tetapi pada tindakan yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan.
Benjamin Moffit dalam The Global Rise of Populism (2016) juga telah mewanti-wanti tentang bahaya politik berdasarkan populisme yang menonjolkan gaya, emosi, dan simbol, namun minim substansi kebijakan. Hal ini bisa berujung pada kekecewaan publik jika retorika tersebut tidak disertai dengan hasil. Karisma tanpa kapabilitas hanya akan memperkuat sinisme. Tentu ini menjadi peringatan keras bahwa dalam jangka panjang, politik pertunjukan tanpa realisasi hanya akan menciptakan ketidakpercayaan publik.
Pada akhirnya, sistem demokrasi yang sehat tidak dibangun oleh pemimpin yang sekadar viral di media sosial. Lebih jauh dari itu, demokrasi menuntut sosok pemimpin yang mampu menggabungkan karisma dengan kapabilitas nyata. Menjadikan kata-kata sebagai janji yang harus ditepati melalui tindakan konkret.
Hanya dengan begitu, kepercayaan publik dapat terbangun kembali, dan perubahan besar yang berkelanjutan bisa terwujud. Karena politik bukan sekadar pertunjukan, melainkan tanggung jawab besar untuk kesejahteraan rakyat.