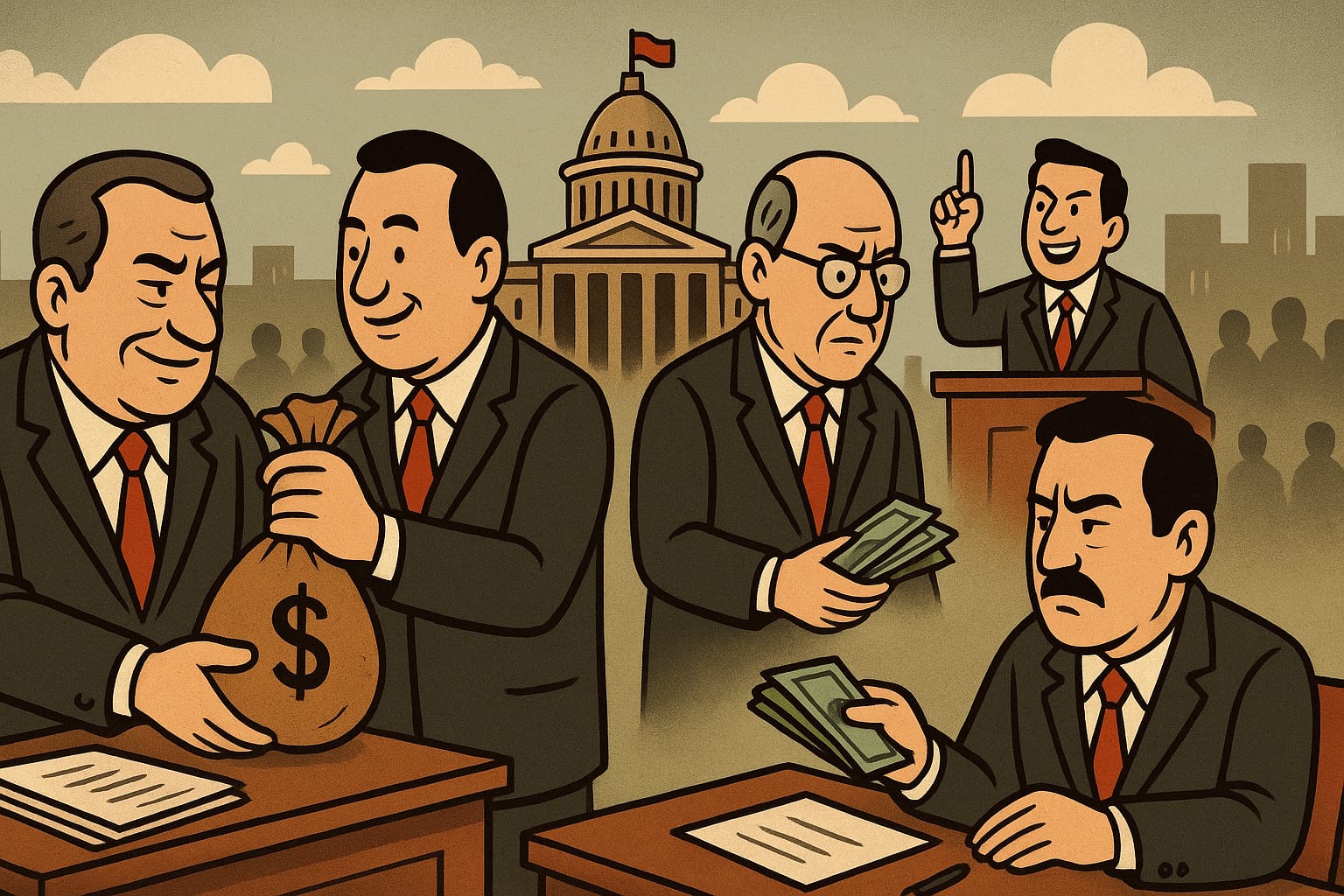MAKLUMAT — Setiap kali pemberitaan mengenai pemimpin politik yang terjerat kasus korupsi memenuhi media, yang muncul bukan hanya rasa kecewa, tetapi juga rasa sedih dan empati yang mendalam. Di balik seragam dinas dan jabatan yang tinggi, mereka adalah manusia yang terjebak dalam sebuah sistem yang kadang lebih kuat dari niat individu.

Selama sepuluh tahun memimpin Bojonegoro, saya menyaksikan langsung bagaimana godaan dan tekanan itu bekerja. Saat kami memilih untuk membangun jalan yang rusak, meningkatkan layanan kesehatan, dan membuka ruang partisipasi publik, di sisi lain, banyak sekali kepentingan yang menuntut “balas jasa”. Mereka yang dahulu mendukung, sering kali berharap imbalan proyek atau akses kebijakan.
Elit politik yang merasa kepentingannya terganggu oleh pemerintahan yang transparan terus menerus menghembuskan kritik dan ancaman. Inilah yang saya sebut sebagai “jerat ekosistem kepemimpinan”—sebuah lingkungan yang secara sistematis mendorong pemimpin untuk menyimpang.
Ekosistem yang Mematikan Integritas
Dalam situasi seperti ini, sangat mudah untuk terjebak dalam narasi “tidak ada pilihan“. Pilihan untuk memenuhi tuntutan partai, untuk membiayai politik transaksional di Pemilu berikutnya, atau sekadar menjaga “kestabilan” koalisi. Korupsi kemudian tidak lagi dilihat sebagai kejahatan, melainkan sebagai “biaya operasional” untuk bertahan dalam kekuasaan.
Pendapat ahli governance, Dr. Johannis L. M. Luitnan, dalam penelitiannya tentang korupsi sistemik, menyatakan, “Ketika struktur insentif dalam sebuah sistem politik lebih banyak menghargai loyalitas buta dan transaksi ekonomi daripada kinerja dan integritas, maka yang terjadi adalah seleksi alam terbalik. Pemimpin yang jujur justru tersingkir, sementara mereka yang adaptif pada sistem korup akan bertahan dan bahkan berkembang.”
Inilah paradoks kepemimpinan kita. Seorang pemimpin yang ingin benar-benar melayani seringkali harus berjalan sendirian, melawan arus besar ekosistem yang sudah terpolusi.
Mencari Pijakan dalam Ajaran Islam
Dalam kegalauan menghadapi realitas ini, keimanan dan ajaran Islam menjadi penuntun yang paling kokoh. Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 188:
Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
Ayat tersebut dengan sangat jelas dan tegas melarang segala bentuk korupsi, suap, dan pengelolaan harta yang batil. Korupsi bukan hanya merusak perekonomian negara, tetapi lebih dari itu, ia adalah kezaliman terhadap hak-hak rakyat dan sebuah dosa yang nyata.
Rasulullah SAW juga bersabda:
Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (HR. Bukhari dan Muslim).
Sabda ini menegaskan bahwa jabatan adalah amanah, bukan kesempatan. Seberat apapun tekanan yang dihadapi, seorang pemimpin muslim tidak boleh melepaskan amanah ini dengan khianat. Pilihan untuk korupsi, dalam perspektif ini, adalah kegagalan spiritual sebelum kegagalan administratif.
Jalan Keluar: Memperkuat Spiritualitas dan Sistem
Lantas, apa yang harus dilakukan? Empati kita kepada mereka yang terjebak tidak boleh berubah menjadi pembenaran. Sebaliknya, empati harus mendorong kita untuk memperbaiki sistem dan memperkuat ketahanan spiritual para calon pemimpin.
Pertama, pendidikan karakter dan spiritualitas aktif. Pendidikan kepemimpinan harus menekankan pada spiritualitas aktif—keyakinan bahwa ibadah ritual harus tercermin dalam integritas sosial. Seperti yang saya alami, keyakinan bahwa “Allah bersamaku” menjadi benteng terkuat menghadapi segala godaan.
Kedua, membangun ekosistem baru. Kita perlu membangun ekosistem politik yang baru, di mana pemimpin dengan integritas didukung oleh sistem pendanaan partai yang transparan, sistem rekrutmen yang sehat, dan penghargaan publik atas kinerja, bukan hanya popularitas.
Ketiga, dukungan dari bawah. Rakyat sebagai pemilih harus cerdas dan tidak permisif. Tidak lagi memilih berdasarkan politik uang atau ikatan primordial sempit, tetapi berdasarkan rekam jejak dan komitmen pelayanan.
Sejarah memberi pesan kuat, perjalanan kepemimpinan di jalan pelayanan publik yang bersih, meski sunyi dan penuh cercaan, adalah mungkin. Ia membutuhkan keteguhan hati, kesabaran, dan keyakinan yang dalam. Perlunya mengenali ekosistem, mentransformasikan organisasi dan keteguhan memperkuat kesadaran diri untuk panggilan yang lebih besar melampaui ego dan kelompok.
Kepada para calon pemimpin muda: persiapkanlah diri kalian tidak hanya dengan kompetensi, tetapi juga dengan benteng spiritual dan mental yang tangguh. Percayalah, “Kebenaran akan ada yang mendengarnya, keindahan akan ada yang melihatnya, dan ketulusan akan ada yang merasakannya.”
Mari bersama-sama membongkar jerat ekosistem koruptif ini dan menggantinya dengan ekosistem kepemimpinan yang berintegritas dan ber-amar ma’ruf nahi munkar.
UMG, 9 November 2025