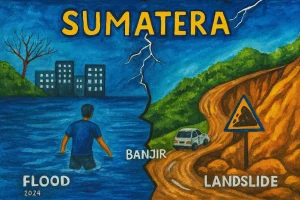MUHAMMADIYAH dikenal sebagai organisasi yang anti terhadap tahayul, bid’ah dan kurofat (TBC). Namun, faktanya tidaklah demikian. Hal yang dianggap sebagai penyakit itu nyatanya masih bergelayutan di alam pikiran dan menjadi prilaku warga Muhammadiyah. TBC itu tidak benar-benar hilang.
Ketika berpolitik, contohnya, warga Persyarikatan ternyata masih percaya dengan tahayul. Hal itu tercermin dari perilaku politik pimpinan Persyarikatan yang lebih mengedepankan hasil terawangan daripada rasionalitas. Elite Muhammadiyah dibeberapa level berlagak menjadi dukun-dukun politik.
Warga Muhammadiyah yang dikenal terdidik dan intelektual itu ketika berpolitik pun masih menggunakan pendekatan emosional dan berhayal ketimbang menggunakan rasionalitas. Ketika berpolitik, Muhammadiyah tanpa data, kajian dan analisa mendalam. Proses politik pun dilakukan secara sporadis, tanpa desain.
Anehnya lagi, sebagian elite pimpinan Muhammadiyah lebih percaya kabar burung yang bertebaran di media sosial. Yang biasanya itu segaja ditebar oleh para buzzer. Celakanya adalah informasi yang kebanyakan hoax dan sifatnya framming itu diterima mentah-mentah dan dipercaya. Aneh bin ajaib memang.
Kepercayaan terhadap tahayul politik pada akhirnya membuat Muhammadiyah tidak luwes ketika menyikapi perbedaan pilihan politik. Warga Muhammadiyah jadi mudah baper. Jadi tidak dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan politik. Kita mudah sekali menyalahkan sesama kader yang berbeda garis politik. Kader dianggap murtad, bahkan divonis tidak lagi Islam karena berbeda pilihan politik.
Pandangan politik yang hitam-putih, banar- salah inilah yang membikin keruh suasana. Jadinya, politik dianggap sebagai barang yang kotor, najis dan harus dijauhi. Setiap kader yang telah bersentuhan dengan partai politik harus wudhu terlebih dulu untuk bisa masuk dan beraktivitas kembali di Persyarikatan.
Maka, kita harus bisa mengambil pelajaran pada edisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019 lalu. Dimana energi Persyarikatan terkuras habis menghadapi sengitnya kontestasi yang nyatanya hanya rutinitas 5 tahunan. Para pimpinan dan warga Persyarikatan mati-matian mendukung salah satu calon yang dinilai ideal. Dikemas sebagai representasi umat Islam. Meski aslinya itu cuma kemasan. Sebagai bumbu penyedap politik.
Tak ayal suasana internal Persyarikatan menjadi panas kala menghadapi tahun politik 2019. Pembelahan pun terjadi. Warga Muhammadiyah dibikin terombang-ambing dalam pusaran dukung mendukung calon. Tanpa hasil. Endingnya pun menyesakan. Calon yang jadi jago warga Muhammadiyah kalah.
Setelahnya, hanya kekecewa yang didapat. Warga Muhammadiyah hanya bisa mengumpat dan ngedumel. “Kok Muhammadiyah tidak diberi jatah menteri dan posisi strategis lainnya”. Lah wong tidak berkeringat dan tidak mendukung kok minta posisi dan jabatan.
Yang memilukan lagi adalah sang calon yang didukung mati-matian oleh warga Muhammadiyah malah bermanuver, menerima pinangan sang rival. Sang calon presiden itu bersedia turun kasta menjadi menteri. Sia-sialah dukungan warga Muhammadiyah.
Nah, perlu diingat nasihat dari Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Abdul Mu’ti bahwa, politik itu ketika pol atau mentok sekalipun, masih bisa diutak atik. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Apalagi soal politik kekuasaan. Semua serba mungkin dan tidak saklek. Kita harus terbiasa menerima perbedaan pilihan politik.
Muhammadiyah Perlu Rasional Berpolitik
Muhammadiyah memang bukan organisasi politik. Juga tidak berpolitik praktis. Tapi segela hal di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik. Ijin pendirian amal usaha Muhammadiyah, misalnya, butuh kerja politik. Pun dengan kegiatan dakwah Muhammadiyah, akan bisa terhambat jika ada tangan jahil politik mengganggu.
Oleh karena itu sudah seyogyanya Muhammadiyah mulai serius melakukan upaya untuk menyiapkan banyak “mubaligh” politik turun berdakwah dalam kancah politik praktis. Ini penting agar politik adiluhung yang digemakan oleh Muhammadiyah, tidak kalah nyaring suaranya dengan pramagtisme politik kekuasaan.
Politik etik yang dipedomani Muhammadiyah juga tidak kalah dengan praktik politik transaksional ala Nicolo Machiavelli, yang menghalalkan segala cara demi meraih dan melanggengkan kekuasaan.
Sejarah mencatat, banyak tokoh Muhammadiyah terjun ke panggung politik kekuasaan. Itu karena Muhammadiyah tidak anti dengan kekuasaan. Muhammadiyah juga bukanlah oposan sebagaimana partai politik yang kalah. Tengoklah Buya Hamka yang mampu menjadi muadzin. Pria asal Minang itu mampu menyuarakan Islam dalam panggung politik kebangsaan.
Selain itu, sebagai organisasi yang mendeklair diri modern dan berkemajuan, cara berpolitik Muhammadiyah harus berubah, tidak boleh lagi berpolitik berdasarkan hasil terawangan. Itu karena proses politik bisa dikalkulasi secara matematis. Berpedoman dari hasil survei, kajian dan dengan data akurat.
Maka dari itu Muhammadiyah perlu mengkapitalisasi potensi politik yang dimilikinya. Muhammadiyah yang memiliki banyak perguruan tinggi, sekolah, lembaga sosial dan lainnya itu harus punya data dan analisa kuat. Sehingga sikap politik yang diambil Muhammadiyah sesuai dengan data dan kajian.
Sebaliknya, jika masih memelihara tahayul politik, bisa dipastikan Muhammadiyah akan semakin terpinggirkan dan dikucilkan dalam belantika perpolitikan nasional. Juga jangan heran apabila Muhammadiyah akan selalu kalah langkah dalam percaturan politik kebangsaan. Muhammadiyah akan selalu menjadi Yatim Piatu dalam politik kekuasaan. Seperti halnya kata Buya Syafii Maarif.
Muhammadiyah juga bisa dipastikan tidak akan lagi dilirik. Muhammadiyah akan ditinggalkan, bahkan segaja disingkirkan karena dianggap mengganggu dalam kancah politik kekuasaan. Mari hapus tahayul politik, dan mulai membangun desain politik berbasis data dan kajian akurat. Bukan lagi berpolitik semata didasarkan dengan hasil terawangan dan emosional. (*)
M. Khoirul Abduh, Penulis adalah Wakil Ketua PWM Jatim